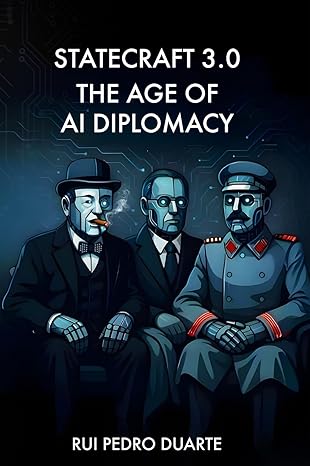Oleh Asep Setiawan
1. Pendahuluan
Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang dimulai secara formal pada tahun 2018, terus mengalami eskalasi dan transformasi hingga tahun 2025, memunculkan konstelasi baru dalam dinamika geoekonomi global. Konfrontasi ekonomi berkepanjangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini telah berevolusi melampaui sekadar konflik tarif bilateral, berkembang menjadi persaingan strategis multidimensi yang mencakup teknologi, investasi, keuangan, dan keamanan ekonomi (Acharya, 2023). Ketegangan geoekonomi ini tidak hanya mempengaruhi kedua protagonis utamanya, tetapi juga secara fundamental mengubah arsitektur ekonomi global, dengan implikasi khusus bagi kawasan Asia Tenggara yang secara geografis dan ekonomis terletak di persimpangan pengaruh kedua negara tersebut.
Asia Tenggara, sebagai kawasan yang secara historis memiliki ketergantungan ekonomi signifikan terhadap baik Amerika Serikat maupun China, menemukan dirinya berada dalam posisi geostrategis yang kompleks. Kawasan ini telah lama menjadi salah satu pusat produksi global, hub perdagangan regional, dan destinasi investasi asing yang penting. Ketika perang dagang berkembang menjadi kompetisi geostrategis yang lebih luas, negara-negara Asia Tenggara menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan politiknya di tengah persaingan kekuatan besar (Thuzar & Deinla, 2022). Dalam konteks ini, Asia Tenggara tidak sekadar menjadi pengamat pasif, melainkan aktor strategis yang respons kebijakannya berpotensi mempengaruhi konfigurasi masa depan ekonomi regional dan global.
Kompleksitas dampak perang dagang terhadap Asia Tenggara tercermin dalam berbagai dimensi ekonominya. Di satu sisi, ketegangan perdagangan telah mendorong relokasi fasilitas produksi dari Tiongkok ke beberapa negara Asia Tenggara, menciptakan pertumbuhan sektor manufaktur dan peningkatan investasi asing langsung (FDI) di negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand (Kimura et al., 2023). Di sisi lain, disrupsi rantai pasok global, penurunan perdagangan internasional, dan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas telah menimbulkan tekanan terhadap ekonomi regional yang sangat bergantung pada ekspor (Tham et al., 2022). Polarisasi ekosistem teknologi dan standar industri sebagai akibat dari rivalitas teknologi AS-Tiongkok juga memaksa negara-negara Asia Tenggara untuk membuat pilihan strategis yang kompleks dengan implikasi jangka panjang.
Esai ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok hingga tahun 2025 terhadap ekonomi Asia Tenggara. Dengan menerapkan pendekatan kritis dan interdisipliner, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan fundamental: Bagaimana perang dagang mempengaruhi aliran perdagangan, investasi, dan konfigurasi rantai pasok di Asia Tenggara? Bagaimana respons kebijakan negara-negara Asia Tenggara terhadap ketegangan geoekonomi ini, dan sejauh mana efektivitasnya? Apakah perang dagang mendorong transformasi struktural positif dalam ekonomi regional, atau sebaliknya memperdalam kerentanan yang sudah ada? Dan akhirnya, bagaimana Asia Tenggara sebagai kawasan dapat memposisikan dirinya secara strategis dalam arsitektur ekonomi global yang sedang berevolusi?
Signifikansi artikel ini terletak pada relevansi kontemporer dan implikasi jangka panjangnya. Di tengah lanskap geopolitik yang semakin tidak pasti dan sistem perdagangan multilateral yang terfragmentasi, memahami bagaimana ekonomi regional merespons dan beradaptasi dengan ketegangan geoekonomi utama menjadi sangat penting bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan akademisi. Analisis ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik tentang ekonomi politik internasional dan studi kawasan, tetapi juga menawarkan wawasan praktis bagi perumusan kebijakan yang dapat meningkatkan ketahanan regional dan posisi strategis Asia Tenggara dalam konstelasi global yang terus berubah.
2. Evolusi Perang Dagang AS-Tiongkok: Konteks Historis dan Perkembangan Terkini
2.1 Akar Historis dan Eskalasi Awal (2018-2020)
Perang dagang AS-Tiongkok secara formal dimulai pada Maret 2018 ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor pada produk baja dan aluminium Tiongkok, yang dengan cepat berkembang menjadi serangkaian eskalasi tarif bilateral (Wu, 2021). Namun, akar dari ketegangan ini jauh lebih dalam dan kompleks. Menurut Steinberg (2022), konfrontasi ekonomi ini berakar pada ketidakseimbangan struktural dalam hubungan perdagangan bilateral, kekhawatiran AS tentang praktik perdagangan Tiongkok yang dianggap tidak adil (termasuk transfer teknologi paksa, subsidi industri, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual), serta persepsi AS bahwa kebangkitan ekonomi Tiongkok menantang hegemoni global Amerika.
Fase awal perang dagang (2018-2020) ditandai oleh eskalasi tarif bilateral yang cepat. Hingga akhir 2019, AS telah mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok senilai lebih dari $360 miliar, sementara Tiongkok membalas dengan tarif pada impor AS senilai $110 miliar (Chen & Yang, 2022). Meskipun Perjanjian Fase Satu ditandatangani pada Januari 2020 sebagai upaya de-eskalasi parsial, ketegangan ekonomi tetap tinggi. Bao dan Zhang (2023) berpendapat bahwa perjanjian ini gagal mengatasi masalah struktural yang mendasari ketegangan perdagangan, sebaliknya hanya memberikan gencatan senjata sementara yang rapuh dalam konfrontasi ekonomi yang lebih luas.
2.2 Transformasi Menuju Persaingan Teknologi dan Keamanan Ekonomi (2020-2023)
Antara tahun 2020 dan 2023, perang dagang mengalami transformasi signifikan, berevolusi dari konfrontasi tarif bilateral menjadi persaingan teknologi multidimensi dan keamanan ekonomi. Pandemi COVID-19 dan disrupsi rantai pasok global yang menyertainya semakin memperburuk ketegangan yang sudah ada, dengan kedua negara memperkuat retorika tentang kemandirian ekonomi dan keamanan rantai pasok nasional (Wang & Chong, 2023).
Periode ini menyaksikan perluasan fokus dari tarif tradisional ke kontrol ekspor teknologi, pemeriksaan investasi asing, dan kebijakan industri domestik. Administrasi Biden, meskipun mengadopsi pendekatan yang lebih multilateral dibandingkan pendahulunya, secara substansial mempertahankan dan bahkan memperluas berbagai pembatasan terhadap Tiongkok, khususnya di sektor teknologi tinggi (Bown, 2022). Pembatasan terhadap perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei dan ZTE, kontrol ekspor pada teknologi semikonduktor canggih, dan inisiatif untuk “de-risking” hubungan ekonomi dengan Tiongkok menjadi komponen utama strategi ekonomi AS (Tan & Mah, 2022).
Tiongkok, sebagai respons, mempercepat upaya untuk mencapai kemandirian teknologi dan mengurangi ketergantungan pada teknologi Barat melalui inisiatif seperti “Made in China 2025” dan kebijakan “Dual Circulation” (Zenglein, 2023). Pemerintah Tiongkok juga meningkatkan dukungan untuk industri strategis domestik, termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan, serta memperluas kehadiran ekonominya di kawasan melalui Inisiatif Sabuk dan Jalur yang semakin matang (Baark, 2022).
2.3 Dinamika Kontemporer dan Kompleksitas Baru (2023-2025)
Perkembangan perang dagang antara 2023 dan 2025 ditandai oleh pola kompleks yang melibatkan kompetisi dan kerjasama terbatas, dengan persaingan strategis yang semakin terlembaga sebagai fitur permanen dalam hubungan bilateral. Lin dan Petri (2024) mencatat bahwa periode ini ditandai oleh empat tren utama yang saling terkait: (1) normalisasi ketegangan ekonomi sebagai “status quo” baru dalam hubungan bilateral; (2) regionalisasi persaingan melalui inisiatif ekonomi yang saling bersaing di kawasan Indo-Pasifik; (3) sektorialisasi persaingan dengan fokus pada teknologi kritis dan rantai pasok strategis; dan (4) multilateralisasi ketegangan dengan upaya dari kedua belah pihak untuk membangun koalisi yang lebih luas.
Kebijakan AS terhadap Tiongkok semakin mencerminkan konsensus bipartisan mengenai perlunya pendekatan yang lebih tegas, dengan fokus pada perlindungan keunggulan teknologi, penguatan rantai pasok domestik, dan pembentukan blok ekonomi dengan negara-negara yang berpikiran sama (Saha & Golley, 2024). Inisiatif seperti Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), pendalaman aliansi teknologi dengan sekutu-sekutu kunci, dan investasi domestik besar-besaran dalam industri strategis melalui undang-undang seperti CHIPS and Science Act dan Inflation Reduction Act mencerminkan strategi multi-dimensi ini (Goodman & Remler, 2023).
Tiongkok, menghadapi hambatan eksternal yang meningkat, telah memperdalam fokusnya pada inovasi domestik, diversifikasi pasar, dan diplomasi ekonomi regional. Zhang dan Li (2024) mengidentifikasi tiga pilar strategi ekonomi Tiongkok: (1) akselerasi transformasi model pertumbuhan melalui inovasi teknologi dan konsumsi domestik; (2) penguatan ketahanan ekonomi melalui kemandirian dalam teknologi kritis dan komoditas strategis; dan (3) perluasan pengaruh ekonomi regional melalui perjanjian perdagangan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan intensifikasi investasi di pasar negara berkembang.
Pada tahun 2025, medan persaingan geoekonomi telah berkembang secara signifikan, dengan pertarungan atas standar teknologi, norma digital, infrastruktur regional, dan arsitektur keuangan menjadi sama pentingnya dengan perdagangan barang tradisional (Tang & Pham, 2025). Persaingan ini telah mendorong terbentuknya dua ekosistem teknologi yang semakin berbeda, dengan konsekuensi mendalam bagi negara-negara yang bergantung pada kedua pasar tersebut, termasuk ekonomi Asia Tenggara.
3. Kerangka Teoretis dan Konseptual
3.1 Teori Interdependensi Kompleks dan Persaingan Geoekonomi
Untuk memahami dinamika perang dagang AS-Tiongkok dan implikasinya terhadap Asia Tenggara, penelitian ini mengadopsi kerangka teoretis interdependensi kompleks yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye, sebagaimana diperbarui oleh Farrell dan Newman (2024) untuk konteks kontemporer. Teori ini mengakui bahwa dalam sistem global yang saling terhubung, hubungan ekonomi menciptakan baik sensitivitas (dampak jangka pendek dari perubahan eksternal) maupun kerentanan (biaya penyesuaian jangka panjang), yang membentuk dinamika kekuasaan antar negara dan respons kebijakan mereka.
Farrell dan Newman (2024, p. 87) berpendapat bahwa “interdependensi global modern telah menciptakan ‘titik-titik penghubung’ (choke points) baru dalam jaringan ekonomi global yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan strategis.” Konsep “senjata interdependensi” ini sangat relevan untuk memahami bagaimana AS dan Tiongkok memanipulasi ketergantungan ekonomi untuk keuntungan strategis, dan bagaimana negara-negara Asia Tenggara menavigasi posisi mereka dalam jaringan interdependensi yang asimetris ini.
Pendekatan geoekonomi, sebagaimana dikembangkan oleh Blackwill dan Harris (2023), juga memberikan lensa analitis yang berharga. Mereka mendefinisikan geoekonomi sebagai “penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan nasional, dan untuk menghasilkan hasil geopolitik yang menguntungkan” (p. 42). Dalam konteks perang dagang AS-Tiongkok, kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin dipolitisasi dan disekuritisasi, dengan implikasi mendalam bagi negara-negara yang berada di persimpangan persaingan kekuatan besar.
3.2 Regionalisme Ekonomi dan Teori Rantai Nilai Global
Untuk menganalisis dampak perang dagang terhadap integrasi ekonomi regional di Asia Tenggara, penelitian ini menggunakan perspektif regionalisme ekonomi yang dikembangkan oleh Katzenstein dan Shiraishi, dan diperluas oleh Hameiri dan Jones (2023). Teori ini mengeksplorasi bagaimana negara-negara dalam satu kawasan mengembangkan mekanisme kerjasama ekonomi sebagai respons terhadap tekanan eksternal, dengan menekankan interaksi antara kekuatan struktural global dan agensi regional.
Hameiri dan Jones (2023, p. 218) berargumen bahwa “regionalisme di Asia Tenggara tidak pernah murni endogen atau otonom, tetapi selalu berkembang dalam konteks kekuatan dan tekanan eksternal.” Pandangan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana ASEAN dan negara-negara anggotanya merespons disrupsi perdagangan global yang disebabkan oleh perang dagang, serta bagaimana mereka berupaya mempertahankan otonomi strategis di tengah persaingan kekuatan besar.
Teori rantai nilai global (GVC), sebagaimana dikembangkan oleh Gereffi dan kemudian dielaborasi oleh Yeung dan Coe (2024), menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis reorganisasi produksi regional sebagai respons terhadap perang dagang. Pendekatan ini menekankan pentingnya struktur tata kelola, peningkatan industri, dan strategi perusahaan dalam menentukan pola perdagangan dan investasi. Yeung dan Coe (2024, p. 156) berpendapat bahwa “geopolitik dan geoekonomi semakin membentuk organisasi dan geografi GVC,” pandangan yang sangat relevan untuk memahami bagaimana ketegangan AS-Tiongkok mempengaruhi arsitektur produksi regional di Asia Tenggara.
3.3 Transformasi Struktural dan Ketahanan Ekonomi Regional
Untuk mengevaluasi implikasi jangka panjang perang dagang terhadap pembangunan ekonomi Asia Tenggara, penelitian ini menggunakan konsep transformasi struktural yang dikembangkan oleh Rodrik dan diperbarui oleh Diao, McMillan, dan Wangwe (2022). Kerangka ini berfokus pada pergeseran sumber daya ekonomi antar sektor dan peningkatan produktivitas sebagai kunci pertumbuhan berkelanjutan, dengan penekanan khusus pada peran kebijakan industri dan kelembagaan dalam memfasilitasi transformasi positif.
Diao et al. (2022, p. 42) mengidentifikasi bahwa “guncangan eksternal dapat baik mempercepat atau menghambat transformasi struktural, tergantung pada kapasitas adaptif ekonomi dan efektivitas respons kebijakan.” Perspektif ini menawarkan lensa berharga untuk mengevaluasi apakah disrupsi yang disebabkan oleh perang dagang mendorong diversifikasi ekonomi produktif dan peningkatan industri di Asia Tenggara, atau sebaliknya, memperkuat pola spesialisasi yang tidak optimal.
Akhirnya, konsep ketahanan ekonomi regional, sebagaimana dikembangkan oleh Martin dan Sunley dan diperbarui oleh Tantri dan Yeo (2023), memberikan kerangka kerja untuk menganalisis kapasitas ekonomi Asia Tenggara untuk menyerap guncangan, beradaptasi dengan perubahan, dan potensial untuk mentransformasi krisis menjadi peluang. Tantri dan Yeo (2023, p. 276) mendefinisikan ketahanan regional sebagai “kapasitas sistem ekonomi regional untuk menahan atau pulih dengan cepat dari guncangan pasar atau lingkungan dan mempertahankan atau mengembalikan fungsi dasar, struktur, dan identitasnya.” Konsep ini sangat relevan untuk mengevaluasi bagaimana berbagai ekonomi Asia Tenggara merespons secara berbeda terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh perang dagang, dan faktor-faktor yang menjelaskan variasi dalam ketahanan mereka.
4. Transformasi Pola Perdagangan Regional
4.1 Dampak terhadap Aliran Perdagangan Trilateral
Perang dagang AS-Tiongkok telah secara fundamental mengubah pola perdagangan trilateral antara AS, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Analisis data perdagangan komprehensif oleh Tham, Kam, dan Jinjarak (2023) menunjukkan pergeseran signifikan dalam komposisi dan arah aliran perdagangan regional antara 2018 dan 2025. Meskipun perdagangan AS-Tiongkok mengalami kontraksi signifikan dalam kategori produk yang terkena tarif, dampak netnya terhadap perdagangan Asia Tenggara menunjukkan pola yang lebih kompleks dan beragam.
Salah satu perkembangan paling signifikan adalah peningkatan ekspor Asia Tenggara ke AS sebagai pengganti produk Tiongkok yang terkena tarif. Vietnam muncul sebagai penerima manfaat utama dari pengalihan perdagangan ini, dengan ekspor ke AS meningkat sebesar 147% antara 2018 dan 2025, terutama dalam kategori elektronik, furnitur, dan tekstil (Nguyen & Park, 2024). Malaysia dan Thailand juga mencatat pertumbuhan ekspor yang kuat ke pasar AS, meskipun dengan skala yang lebih kecil. Secara keseluruhan, pangsa Asia Tenggara dalam impor AS meningkat dari 8,2% pada 2018 menjadi 14,7% pada 2025, sementara pangsa Tiongkok menurun dari 21,6% menjadi 16,2% dalam periode yang sama (Kimura et al., 2023).
Namun, perlu dicatat bahwa pengalihan perdagangan ini tidak terdistribusi secara merata di seluruh kawasan. Sebagaimana diidentifikasi oleh Sanchita (2023, p. 143), “hanya negara-negara dengan kapasitas manufaktur yang sudah mapan, infrastruktur logistik yang baik, dan hubungan yang sudah ada dengan rantai pasokan global yang mampu memanfaatkan sepenuhnya peluang pengalihan perdagangan.” Ini menjelaskan mengapa Vietnam, Malaysia, dan Thailand telah mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan negara seperti Indonesia, Filipina, atau ekonomi Mekong yang kurang berkembang.
Perang dagang juga menyebabkan perubahan dalam hubungan perdagangan Asia Tenggara-Tiongkok. Meskipun Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar kawasan ini, komposisi perdagangan telah bergeser. Ekspor bahan baku dan barang setengah jadi dari Asia Tenggara ke Tiongkok meningkat secara signifikan, mencerminkan integrasi yang lebih dalam ke dalam rantai pasokan yang berpusat di Tiongkok untuk melayani pasar domestik Tiongkok dan pasar pihak ketiga yang tidak terkena tarif AS (Tham et al., 2023). Pola ini juga mencerminkan strategi perusahaan multinasional yang berbasis di Tiongkok untuk memindahkan tahap produksi akhir ke Asia Tenggara untuk menghindari tarif AS, sambil mempertahankan aktivitas hulu di Tiongkok.
Dimensi perdagangan jasa juga mengalami transformasi penting, meskipun sering kali kurang mendapat perhatian dalam analisis perang dagang. Peng dan Rajah (2024) mengidentifikasi peningkatan yang signifikan dalam ekspor jasa digital dari negara-negara Asia Tenggara, terutama Singapura, Indonesia, dan Malaysia, yang sebagian didorong oleh strategi diversifikasi perusahaan teknologi Tiongkok dan AS yang berupaya mengurangi eksposur langsung mereka terhadap risiko geopolitik.
4.2 Diversifikasi Pasar dan Pengembangan Konektivitas Intra-Regional
Ketidakpastian yang diciptakan oleh perang dagang telah mempercepat upaya diversifikasi pasar oleh negara-negara Asia Tenggara. Menariknya, meskipun ekspor ke AS dan Tiongkok tetap penting, kawasan ini secara kolektif telah mengurangi ketergantungan relatifnya pada kedua pasar tersebut. Data dari Asian Development Bank (ADB) yang dianalisis oleh Menon dan Beverinotti (2024) menunjukkan bahwa antara 2018 dan 2025, pangsa gabungan AS dan Tiongkok dalam total ekspor ASEAN menurun dari 30,5% menjadi 28,1%, sementara perdagangan intra-ASEAN meningkat dari 23,4% menjadi 27,8%.
Implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2022 dan pendalaman kerangka ASEAN Economic Community telah memainkan peran penting dalam memperkuat integrasi perdagangan intra-regional. Menurut Ing dan Pangestu (2023, p. 217), “RCEP telah memberikan dorongan baru untuk integrasi ekonomi regional di tengah ketidakpastian global, dengan pengurangan tarif intra-regional dan harmonisasi aturan asal usul barang yang memfasilitasi pengembangan rantai pasokan regional.” Implementasi penuh RCEP diperkirakan akan meningkatkan perdagangan intra-regional sebesar 10,4% pada tahun 2025 dibandingkan dengan skenario tanpa perjanjian.
Studi oleh Park, Petri, dan Plummer (2024) mengidentifikasi tiga pendorong utama peningkatan perdagangan intra-regional: (1) strategi diversifikasi perusahaan multinasional yang mencari pengurangan risiko melalui jaringan produksi yang lebih terdistribusi; (2) peningkatan pendapatan dan kapasitas konsumsi dalam kawasan yang mendorong permintaan domestik; dan (3) kebijakan pemerintah yang ditargetkan untuk mempromosikan perdagangan intra-regional sebagai strategi ketahanan ekonomi.
Perkembangan penting lainnya adalah penguatan hubungan perdagangan dengan ekonomi menengah di luar kawasan, seperti Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan India. Secara khusus, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif UE-Indonesia yang disimpulkan pada tahun 2023 dan implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif India-ASEAN yang dipercepat pada tahun 2024 telah memperluas opsi diversifikasi pasar (Kimura et al., 2023). Dalam periode yang sama, Jepang dan Korea Selatan secara signifikan memperdalam keterlibatan ekonomi mereka dengan kawasan melalui peningkatan investasi dan inisiatif perdagangan, sebagian didorong oleh kebutuhan mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Tiongkok (Tan & Mah, 2022).
Namun, kemajuan dalam diversifikasi pasar tidak merata di seluruh kawasan. Negara-negara dengan ekonomi yang lebih besar dan terdiversifikasi seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia telah menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalihkan ekspor mereka ke pasar alternatif, sementara ekonomi yang lebih kecil dan kurang berkembang menghadapi kendala kapasitas yang lebih signifikan (Menon & Beverinotti, 2024). Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam struktur ekonomi, kapasitas produksi, dan hubungan perdagangan yang sudah ada.
4.3 Reorientasi Strategi Ekspor dan Dilema Kebijakan Perdagangan
Perang dagang telah memaksa negara-negara Asia Tenggara untuk mengevaluasi kembali dan menyesuaikan strategi ekspor mereka. Berbeda dengan pandangan simplistik bahwa kawasan ini semata-mata mendapat keuntungan dari pengalihan perdagangan, realitasnya jauh lebih kompleks. Disrupsi perdagangan global telah menimbulkan dilema kebijakan yang signifikan, memaksa pemerintah untuk menyeimbangkan peluang jangka pendek dengan pertimbangan strategis jangka panjang.
Penelitian oleh Toh dan Chaisse (2023) mengidentifikasi munculnya tiga pendekatan berbeda terhadap strategi ekspor di Asia Tenggara sebagai respons terhadap perang dagang: (1) strategi “China Plus One” yang mempromosikan kawasan sebagai lokasi produksi komplementer namun tidak sepenuhnya menggantikan Tiongkok (diadopsi oleh Vietnam, Thailand, dan Malaysia); (2) pendekatan “nilai tambah nasional” yang memprioritaskan pengembangan kapasitas industri domestik dan mengurangi ketergantungan pada rantai nilai global (diadvokasi terutama oleh Indonesia); dan (3) model “hub teknologi dan jasa” yang memposisikan ekonomi sebagai perantara penting dalam aliran data, keuangan, dan layanan bernilai tinggi (dipimpin oleh Singapura).
Pemilihan pendekatan strategis ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur ekonomi yang ada, kapasitas kelembagaan, dan pertimbangan geopolitik. Seperti yang diamati oleh Toh dan Chaisse (2023, p. 189), “pilihan ini mencerminkan perbedaan fundamental dalam model pembangunan dan bagaimana negara-negara memahami jalur optimal mereka untuk meningkatkan posisi mereka dalam ekonomi global.”
Sementara itu, ketidakpastian dalam sistem perdagangan global telah menciptakan dilema kebijakan yang akut bagi pembuat kebijakan di Asia Tenggara. Pertama, terdapat ketegangan antara memanfaatkan keuntungan jangka pendek dari pengalihan perdagangan versus mengejar transformasi struktural jangka panjang. Sanchita (2023, p. 156) berpendapat bahwa “fokus berlebihan pada pengambilalihan produksi berintensitas tenaga kerja yang beralih dari Tiongkok dapat mengunci ekonomi Asia Tenggara dalam aktivitas bernilai rendah dan menghambat peningkatan industri jangka panjang.”
Kedua, pembuat kebijakan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan hubungan ekonomi dengan AS dan Tiongkok. Meskipun kawasan secara keseluruhan telah berusaha mempertahankan netralitas strategis, tekanan untuk memilih sisi dalam bidang-bidang seperti standar teknologi, pengadaan infrastruktur, dan keterlibatan dalam inisiatif ekonomi yang dipimpin oleh kekuatan besar telah meningkat (Thuzar & Deinla, 2022). Dilema ini telah menyebabkan pendekatan yang lebih berhati-hati dan pragmatis terhadap perjanjian perdagangan dan investasi baru.
Ketiga, terdapat perdebatan tentang keseimbangan optimal antara keterbukaan ekonomi dan kemandirian strategis. Krisis rantai pasokan selama pandemi COVID-19, dikombinasikan dengan ketegangan geopolitik yang meningkat, telah memperkuat argumen untuk kemandirian yang lebih besar dalam sektor-sektor kritis. Namun, seperti yang dicatat oleh Ing dan Pangestu (2023, p. 223), “ekonomi Asia Tenggara tetap sangat bergantung pada perdagangan internasional untuk pertumbuhan dan pembangunan, membuat pendekatan proteksionis menjadi kontraproduktif.” Menyeimbangkan ketahanan ekonomi dengan keuntungan dari integrasi global tetap menjadi tantangan kebijakan utama.
5. Rekonfigurasi Rantai Pasok Regional dan Investasi Asing Langsung
5.1 Relokasi Industri dan Restrukturisasi Jaringan Produksi
Salah satu dampak paling nyata dari perang dagang terhadap ekonomi Asia Tenggara adalah rekonfigurasi signifikan rantai pasok regional dan pola investasi asing langsung (FDI). Menurut analisis komprehensif oleh Kimura, Obashi, dan Thangavelu (2023), tiga gelombang berbeda dalam restrukturisasi rantai pasok regional dapat diidentifikasi antara 2018 dan 2025: gelombang pertama (2018-2020) didorong terutama oleh penghindaran tarif langsung; gelombang kedua (2020-2022) dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan kekhawatiran ketahanan rantai pasok; dan gelombang ketiga (2022-2025) mencerminkan pertimbangan strategis jangka panjang terkait persaingan teknologi dan tekanan untuk “de-risking” atau “friend-shoring”.
Data dari UNCTAD yang dianalisis oleh Ing dan Pangestu (2023) menunjukkan bahwa antara 2018 dan 2025, arus FDI ke Asia Tenggara meningkat sebesar 78%, dengan pertumbuhan terkuat dalam manufaktur elektronik, komponen otomotif, peralatan medis, dan tekstil teknis. Penambahan kapasitas manufaktur signifikan diamati di Vietnam (peningkatan 214%), Malaysia (105%), Thailand (83%), dan Indonesia (64%), sementara Singapura memperkuat posisinya sebagai pusat koordinasi regional dan pusat R&D.
Studi oleh Raghavan dan Kim (2024) mengidentifikasi lima pola utama dalam restrukturisasi rantai pasok di Asia Tenggara:
- Realokasi selektif: Alih-alih relokasi penuh dari Tiongkok, pola dominan yang muncul adalah pendekatan “China Plus One” di mana perusahaan mempertahankan operasi signifikan di Tiongkok sambil mengembangkan kapasitas paralel di Asia Tenggara sebagai strategi mitigasi risiko.
- Spesialisasi regional: Rantai pasok di kawasan menjadi semakin terfragmentasi secara geografis berdasarkan keunggulan komparatif khusus, dengan Vietnam mendominasi elektronik konsumen dan tekstil, Thailand kuat dalam komponen otomotif dan kimia, Malaysia berfokus pada semikonduktor dan perangkat medis, dan Indonesia berkembang dalam pengolahan bahan mentah dan manufaktur berorientasi sumber daya.
- Pendalaman rantai pasok lokal: Berbeda dengan pola sebelumnya di mana manufaktur Asia Tenggara sangat bergantung pada input menengah dari Tiongkok, terdapat upaya yang semakin besar untuk mengembangkan kapasitas pemasok lokal, didorong oleh kekhawatiran tentang gangguan rantai pasok dan ketentuan aturan asal usul barang yang lebih ketat dalam perjanjian perdagangan.
- Digitalisasi dan otomatisasi yang dipercepat: Perusahaan yang merelokasi ke Asia Tenggara semakin berinvestasi dalam teknologi manufaktur canggih dan solusi digital, menghasilkan “generasi baru” fasilitas yang lebih intensif modal dan teknologi dibandingkan gelombang investasi sebelumnya.
- Reorientasi pasar: Meskipun ekspor ke AS tetap penting, investasi baru semakin ditargetkan untuk melayani pasar regional Asia dan pasar domestik Asia Tenggara yang berkembang, mencerminkan strategi diversifikasi pasar yang lebih luas.
Rekonfigurasi rantai pasok ini memiliki implikasi penting untuk pembangunan ekonomi regional. Di satu sisi, ini telah menciptakan peluang signifikan untuk penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan industri. Di sisi lain, Raghavan dan Kim (2024, p. 178) memperingatkan bahwa “tanpa kebijakan yang tepat, Asia Tenggara berisiko terjebak dalam posisi menengah dalam rantai nilai global, melakukan tugas-tugas bernilai tambah rendah tanpa memperoleh kemampuan kritis untuk meningkatkan ke aktivitas yang lebih maju.”
5.2 Investasi Asing Langsung: Tren, Pola, dan Motivasi Strategis
Perang dagang telah menghasilkan perubahan substantif dalam volume, komposisi, dan motivasi di balik arus FDI ke Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Asian Development Bank yang dianalisis oleh Dezan Shira and Associates (2023), total FDI ke kawasan meningkat dari $155 miliar pada tahun 2018 menjadi $276 miliar pada tahun 2025, dengan perubahan penting dalam sumber dan targetnya.
Analisis komprehensif oleh Pham dan Vines (2024) mengidentifikasi tiga pergeseran utama dalam lanskap FDI regional:
Pertama, terjadi diversifikasi signifikan dalam sumber FDI. Meskipun Tiongkok tetap menjadi investor penting (menyumbang 18,7% dari total FDI pada tahun 2025), kontribusi relatifnya telah menurun dari puncak 26,3% pada tahun 2019. Sementara itu, investasi dari AS, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan semakin banyak dari Taiwan dan India telah meningkat secara substansial. Secara khusus, investasi dari perusahaan multinasional berbasis AS meningkat 120% antara 2018 dan 2025, meskipun ketegangan geopolitik yang lebih luas (Kimura et al., 2023).
Kedua, motivasi di balik keputusan investasi telah menjadi lebih kompleks dan multidimensi. Jika investasi sebelumnya ke Asia Tenggara sebagian besar didorong oleh biaya tenaga kerja yang rendah dan akses ke sumber daya alam, penelitian oleh Pham dan Vines (2024, p. 209) mengidentifikasi rangkaian pertimbangan yang lebih luas: “Perusahaan multinasional semakin mengevaluasi lokasi Asia Tenggara berdasarkan kombinasi faktor-faktor termasuk mitigasi risiko geopolitik, kesesuaian dengan strategi ‘China Plus One’, keamanan rantai pasok, akses ke bakat teknis, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan potensi pasar domestik.”
Ketiga, terdapat pergeseran penting dalam komposisi sektoral FDI. Sementara manufaktur tetap dominan (menyumbang 52% dari FDI pada 2025), terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam investasi di bidang teknologi digital, energi terbarukan, dan infrastruktur. Secara khusus, FDI dalam ekonomi digital meningkat dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 34% antara 2018 dan 2025, dengan Singapura, Indonesia, dan Malaysia menjadi penerima utama (Pham & Vines, 2024).
Menariknya, persaingan antara AS dan Tiongkok untuk pengaruh ekonomi telah menghasilkan pendekatan yang berbeda terhadap investasi di kawasan. Investasi Tiongkok tetap terkonsentrasi pada infrastruktur besar, proyek energi, dan manufaktur, sebagian besar dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalur. Sebaliknya, investasi AS dan sekutunya semakin berfokus pada sektor-sektor teknologi tinggi, ekonomi digital, dan manufaktur canggih, seringkali terkait dengan inisiatif “friend-shoring” (Dezan Shira and Associates, 2023).
Dinamika ini menciptakan baik peluang maupun tantangan bagi negara-negara Asia Tenggara. Di satu sisi, persaingan antara AS dan Tiongkok untuk pengaruh ekonomi telah meningkatkan posisi tawar kawasan dan memperluas pilihan sumber pendanaan pembangunan. Di sisi lain, ini juga menciptakan tekanan untuk memilih sisi dalam proyek-proyek strategis, dengan potensi implikasi geopolitik jangka panjang (Tham et al., 2022).
5.3 Tantangan dan Peluang untuk Peningkatan Industri Regional
Rekonfigurasi rantai pasok dan pola investasi baru yang dipicu oleh perang dagang telah menciptakan peluang substansial untuk peningkatan industri di Asia Tenggara, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan. Untuk memanfaatkan sepenuhnya dinamika ini untuk pembangunan ekonomi jangka panjang, negara-negara di kawasan perlu mengatasi berbagai kendala struktural dan mengembangkan strategi yang koheren.
Studi mendalam oleh Raghavan dan Kim (2024) mengidentifikasi empat tantangan utama yang menghambat peningkatan industri regional. Pertama, meskipun terjadi peningkatan FDI, integrasi dengan industri lokal tetap terbatas. Banyak investasi baru beroperasi sebagai “enklaf ekspor” dengan keterkaitan terbatas dengan ekonomi domestik, membatasi potensi untuk transfer teknologi dan peningkatan kemampuan lokal. Kedua, kesenjangan keterampilan dan kapasitas inovasi yang persisten menghambat transisi ke aktivitas bernilai lebih tinggi, dengan investasi dalam penelitian dan pengembangan di sebagian besar negara Asia Tenggara tetap di bawah 1% dari PDB. Ketiga, infrastruktur fisik dan digital yang tidak merata di kawasan menciptakan “ekonomi dua kecepatan”, dengan beberapa wilayah terintegrasi dengan baik ke dalam rantai nilai global sementara yang lain tetap terpinggirkan. Keempat, fragmentasi kebijakan dan persaingan antarnegara ASEAN untuk menarik investasi yang sama sering kali menghasilkan “perlombaan ke dasar” dalam insentif fiskal dan standar lingkungan.
Namun, terdapat juga peluang signifikan untuk peningkatan industri. Analisis oleh Ing dan Pangestu (2023) mengidentifikasi lima jalur potensial untuk peningkatan dan diversifikasi ekonomi yang dapat difasilitasi oleh rekonfigurasi rantai pasok saat ini:
- Pengembangan ekosistem pemasok lokal: Disrupsi dalam rantai pasok global telah meningkatkan insentif bagi perusahaan multinasional untuk mengembangkan basis pemasok lokal yang lebih kuat, menciptakan peluang untuk perusahaan Asia Tenggara untuk terintegrasi ke dalam rantai nilai global. Contoh yang menjanjikan termasuk pertumbuhan pemasok komponen otomotif lokal di Thailand dan ekosistem elektronik di Malaysia dan Vietnam.
- Adopsi teknologi dan digitalisasi: Gelombang investasi baru umumnya membawa teknologi dan praktik bisnis yang lebih canggih, menawarkan peluang untuk modernisasi industri. Program seperti Thailand 4.0 dan Making Indonesia 4.0 berupaya memanfaatkan investasi asing untuk mendorong transformasi digital ekonomi domestik.
- Diversifikasi ke sektor baru: Pergeseran dalam pola perdagangan global membuka peluang untuk diversifikasi ke industri baru di mana Asia Tenggara memiliki keunggulan potensial, seperti bioteknologi, ekonomi hijau, dan layanan digital. Singapura dan Malaysia telah mulai mengembangkan keahlian dalam manufaktur peralatan medis canggih, sementara Indonesia dan Vietnam memperluas kapasitas mereka dalam ekonomi digital.
- Pengembangan kemampuan R&D dan desain: Beberapa perusahaan multinasional mulai membangun pusat R&D dan kemampuan desain di Asia Tenggara, didorong oleh ketersediaan bakat teknis dan insentif pemerintah. Singapura telah muncul sebagai hub R&D regional yang signifikan, sementara Thailand dan Malaysia semakin menarik aktivitas pengembangan produk dalam sektor-sektor tertentu.
- Regionalisasi dan pengembangan pasar domestik: Pertumbuhan kelas menengah di kawasan dan pendalaman integrasi ekonomi regional menciptakan peluang untuk membangun industri yang melayani permintaan regional, mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor tradisional yang tidak pasti.
Realisasi peluang-peluang ini akan membutuhkan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi. Ing dan Pangestu (2023, p. 231) berpendapat bahwa “kebijakan yang mendukung peningkatan industri harus melampaui insentif fiskal tradisional untuk mencakup investasi dalam pengembangan keterampilan, infrastruktur digital, kapasitas inovasi, dan kerangka kerja kelembagaan yang mendukung.”
6. Respons Kebijakan dan Strategi Adaptasi
6.1 Strategi Nasional: Variasi dan Konvergensi
Respons kebijakan negara-negara Asia Tenggara terhadap perang dagang AS-Tiongkok menunjukkan kombinasi menarik antara variasi yang mencerminkan kekhasan konteks nasional dan konvergensi dalam tema-tema strategis yang lebih luas. Studi komparatif oleh Wong dan Chen (2024) menganalisis evolusi strategi ekonomi di enam ekonomi ASEAN utama (Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina) antara 2018 dan 2025, mengidentifikasi baik perbedaan maupun kesamaan dalam pendekatan mereka.
Singapura, sebagai ekonomi paling maju di kawasan dengan ketergantungan besar pada perdagangan internasional, mengadopsi strategi yang menekankan posisinya sebagai hub netral untuk perdagangan, keuangan, dan layanan bisnis. Pemerintah Singapura secara agresif mempromosikan inisiatif untuk memperkuat peran negara kota ini sebagai “Switzerland Asia” dan pusat mediasi ekonomi, sambil secara strategis memposisikan dirinya dalam sektor-sektor seperti kecerdasan buatan, teknologi keuangan, dan bioteknologi (Wong & Chen, 2024). Proyek seperti Global Technology Innovation Hub dan Digital Economy Framework Agreements dengan berbagai mitra menggambarkan pendekatan yang berfokus pada memperkuat peran Singapura sebagai simpul kritis dalam jaringan ekonomi global.
Malaysia mengambil pendekatan yang lebih berorientasi pada manufaktur, membangun infrastruktur industri yang sudah mapan sambil berupaya meningkatkan kecanggihan teknologi. Sesuai dengan Rencana Pertumbuhan Strategis 2030, pemerintah Malaysia memprioritaskan lima sektor: semikonduktor dan elektronik canggih, ekonomi digital, manufaktur berkelanjutan, ekonomi perawatan kesehatan, dan pertanian cerdas (Kimura et al., 2023). Menariknya, kebijakan Malaysia semakin menekankan pembangunan kemampuan nasional dan peningkatan konten lokal, mencerminkan keseimbangan yang diperbarui antara keterbukaan terhadap investasi asing dan pengembangan kapasitas domestik.
Vietnam muncul sebagai salah satu penerima manfaat utama dari perang dagang, dengan pendekatan kebijakan yang memanfaatkan momentumnya sebagai tujuan relokasi utama dari Tiongkok. Strategi Vietnam berfokus pada memperdalam integrasi ke dalam rantai nilai global, menarik investasi manufaktur berorientasi ekspor, dan secara bertahap meningkatkan nilai tambah domestik (Nguyen & Park, 2024). Program investasi infrastruktur besar-besaran, ekspansi zona ekonomi khusus, dan reformasi untuk meningkatkan kemudahan berbisnis menjadi komponen kunci dari strategi Vietnam.
Indonesia, dengan ekonomi terbesar di kawasan dan pasar domestik yang besar, mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi ke dalam yang menekankan pengembangan industri nasional dan substitusi impor. Program Making Indonesia 4.0 dan strategi hilirisasi yang mewajibkan pengolahan domestik komoditas sebelum ekspor mencerminkan fokus pada peningkatan nilai tambah domestik dan pengurangan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah (Ing & Pangestu, 2023). Namun, untuk beberapa sektor strategis seperti kendaraan listrik dan ekonomi digital, Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap investasi asing, menciptakan “pendekatan dua jalur” terhadap integrasi ekonomi global.
Thailand, dengan sektor manufaktur yang sudah mapan, mengejar strategi transformasi ekonomi yang lebih komprehensif melalui inisiatif Thailand 4.0, yang bertujuan menggeser ekonomi menuju industri berbasis pengetahuan dan nilai tambah tinggi. Fokus khusus diberikan pada pengembangan Koridor Ekonomi Timur sebagai hub untuk industri-industri masa depan, termasuk mobilitas cerdas, biofuel, dan robotika (Kimura et al., 2023). Kebijakan Thailand mencerminkan kesadaran tentang persaingan regional yang intensif untuk investasi manufaktur dan kebutuhan untuk membedakan ekonominya dari tetangga dengan biaya lebih rendah seperti Vietnam.
Filipina mengambil pendekatan yang memanfaatkan keunggulan kompetitifnya dalam layanan berbasis pengetahuan sambil berusaha membangun kembali basis manufakturnya. Program Create, Innovate, and Transform dan fokus pada ekonomi kreasi digital mencerminkan strategi untuk memposisikan ekonomi pada segmen bernilai lebih tinggi dari rantai nilai global (Wong & Chen, 2024). Upaya untuk menarik investasi “reshoring” dari perusahaan multinasional Filipina juga menjadi fitur penting dari strategi ekonomi negara ini.
Meskipun terdapat perbedaan penting dalam pendekatan nasional, Wong dan Chen (2024, p. 198) mengidentifikasi empat area konvergensi kebijakan di seluruh kawasan:
- Prioritas untuk diversifikasi ekonomi dan ketahanan: Semua enam negara menerapkan inisiatif untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal melalui diversifikasi mitra dagang, sektor ekonomi, dan rantai pasok.
- Fokus pada digitalisasi dan ekonomi berbasis data: Transformasi digital menjadi prioritas kebijakan utama di seluruh kawasan, dengan investasi substansial dalam infrastruktur digital, keterampilan, dan kerangka regulasi.
- Peningkatan penekanan pada kebijakan industri: Bahkan ekonomi yang paling berorientasi pasar di kawasan telah mengadopsi bentuk-bentuk kebijakan industri yang lebih aktif, dengan dukungan pemerintah yang ditargetkan untuk sektor-sektor strategis dan teknologi.
- Pergeseran menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan: Kebijakan ekonomi di seluruh kawasan semakin menekankan keberlanjutan lingkungan, inklusi sosial, dan ketahanan terhadap perubahan iklim, mencerminkan kesadaran bahwa model pembangunan sebelumnya tidak lagi memadai.
6.2 Respons Kolektif ASEAN: Peluang dan Kendala
Perang dagang AS-Tiongkok telah memberikan baik momentum baru maupun tantangan bagi upaya kerjasama ekonomi kolektif di Asia Tenggara. ASEAN, sebagai organisasi regional utama, telah berupaya mengembangkan respons bersama terhadap perubahan lanskap ekonomi global, meskipun menghadapi kendala kelembagaan dan kepentingan nasional yang beragam.
Menurut analisis mendalam oleh Thuzar dan Deinla (2022), respons kolektif ASEAN terhadap perang dagang berkembang melalui tiga fase berbeda. Fase pertama (2018-2020) ditandai oleh sikap reaktif dan terfragmentasi, dengan negara-negara anggota sebagian besar mengejar strategi nasional individualistis. Fase kedua (2020-2022) menyaksikan peningkatan koordinasi, didorong oleh pandemi COVID-19 dan kesadaran akan kebutuhan untuk merespons secara kolektif terhadap disrupsi rantai pasok. Fase ketiga (2022-2025) menunjukkan pendekatan yang lebih strategis dan kohesif, dengan beberapa inisiatif regional penting yang diluncurkan untuk menangani tantangan dan peluang yang diciptakan oleh rekonfigurasi ekonomi global.
Inisiatif kunci dalam respons kolektif ASEAN mencakup:
- ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF): Diluncurkan pada tahun 2020 dan diperluas pada tahun 2023, kerangka kerja ini memberikan cetak biru untuk pemulihan pasca-pandemi yang juga menangani dampak perang dagang. Komponen utamanya mencakup penguatan ketahanan rantai pasok, akselerasi transformasi digital, dan promosi pembangunan berkelanjutan (Thuzar & Deinla, 2022).
- ASEAN Investment Facilitation Framework (AIFF): Diperkenalkan pada tahun 2021, inisiatif ini bertujuan memanfaatkan peluang yang muncul dari rekonfigurasi rantai pasok global dengan menyederhanakan dan mengharmonisasi prosedur investasi di seluruh kawasan (Kimura et al., 2023).
- ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Negosiasi dimulai pada tahun 2022 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2025, perjanjian ini bertujuan untuk mempercepat integrasi ekonomi digital regional dan membangun ekosistem digital yang terhubung di seluruh kawasan (Wong & Chen, 2024).
- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Meskipun negosiasi dimulai sebelum perang dagang, implementasinya pada tahun 2022 menjadi lebih signifikan dalam konteks ketidakpastian perdagangan global. RCEP memperkuat integrasi ekonomi regional dan memberikan kerangka kerja untuk pengembangan rantai nilai yang lebih terintegrasi di kawasan yang lebih luas (Ing & Pangestu, 2023).
- ASEAN Supply Chain Resilience Initiative (ASCRI): Diluncurkan pada tahun 2023, inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan rantai pasok regional melalui diversifikasi sumber pasokan, digitalisasi manajemen rantai pasok, dan pengembangan kapasitas pemasok lokal (Kimura et al., 2023).
Meskipun inisiatif-inisiatif ini menunjukkan kemauan politik yang signifikan untuk respons kolektif, efektivitasnya dibatasi oleh beberapa kendala struktural. Thuzar dan Deinla (2022, p. 167) mengidentifikasi empat hambatan utama untuk koordinasi kebijakan ASEAN yang efektif dalam merespons perang dagang:
Pertama, prinsip non-interferensi dan pengambilan keputusan konsensus ASEAN sering menyebabkan pendekatan “common denominator terendah” terhadap tantangan bersama. Pada masalah-masalah yang secara geopolitik sensitif seperti menavigasi persaingan AS-Tiongkok, mencapai konsensus menjadi sangat sulit.
Kedua, disparitas tingkat pembangunan dan prioritas ekonomi di antara negara-negara anggota menghasilkan kepentingan yang berbeda dan terkadang bertentangan. Seperti yang dicatat oleh Thuzar dan Deinla (2022, p. 171), “apa yang mungkin dilihat sebagai peluang oleh Vietnam atau Malaysia mungkin diinterpretasikan sebagai ancaman oleh Indonesia atau Filipina, membuat respons kebijakan terpadu menjadi tantangan.”
Ketiga, ASEAN menghadapi keterbatasan kapasitas dan sumber daya kelembagaan untuk mengimplementasikan inisiatif ambisius. Dengan staf dan anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan organisasi regional lainnya seperti Uni Eropa, kapasitas ASEAN untuk mengkoordinasikan respons regional yang kompleks terhadap tantangan global tetap terbatas.
Keempat, tekanan eksternal dari kekuatan besar, khususnya AS dan Tiongkok, sering membuat ASEAN sulit untuk mempertahankan posisi yang benar-benar otonom dan bersatu. Upaya kedua kekuatan untuk menarik negara-negara ASEAN individu ke dalam orbit mereka, baik melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative atau Indo-Pacific Economic Framework, sering kali menguji solidaritas dan kohesi regional.
Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Thuzar dan Deinla (2022, p. 178) menyimpulkan bahwa “ASEAN telah menunjukkan kapasitas adaptif yang mengesankan dalam merespons perubahan dinamika ekonomi global, dan perang dagang telah menciptakan momentum baru untuk pendalaman integrasi ekonomi regional.” Secara khusus, kesadaran bersama akan kerentanan terhadap guncangan eksternal telah memperkuat dukungan politik untuk inisiatif yang memperkuat otonomi strategis dan ketahanan ekonomi kolektif kawasan.
6.3 Kebijakan Industri dan Strategi Transformasi Digital
Perang dagang AS-Tiongkok telah mempercepat adopsi pendekatan kebijakan industri yang lebih aktif di seluruh Asia Tenggara, menandai pergeseran dari paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pasar yang dominan pada dekade-dekade sebelumnya. Menurut Wong dan Chen (2024, p. 203), “ketidakpastian dalam sistem perdagangan global dan pertimbangan keamanan ekonomi telah melegitimasi kembali kebijakan industri sebagai alat untuk mengarahkan transformasi ekonomi dan membangun keunggulan kompetitif nasional.”
Analisis komparatif oleh Ing dan Pangestu (2023) mengidentifikasi tiga jenis utama kebijakan industri yang muncul di kawasan sebagai respons terhadap perang dagang:
- Kebijakan industri vertikal tradisional: Beberapa negara, terutama Indonesia dan dalam tingkat lebih rendah Thailand dan Malaysia, telah menerapkan kebijakan yang menargetkan sektor spesifik untuk promosi, termasuk subsidi, perlindungan pasar, dan insentif fiskal. Indonesia, misalnya, telah mengadopsi kebijakan hilirisasi yang kuat untuk meningkatkan nilai tambah domestik dalam pengolahan sumber daya alam, sementara Thailand telah mengidentifikasi sepuluh “industri target” untuk dukungan khusus dalam kerangka Thailand 4.0 (Ing & Pangestu, 2023).
- Kebijakan industri horizontal: Pendekatan yang lebih umum melibatkan dukungan untuk kemampuan industri lintas sektor tanpa memilih “pemenang” spesifik. Singapura dan Malaysia telah menjadi pemimpin dalam jenis kebijakan ini, dengan program yang mendukung inovasi, digitalisasi, peningkatan keterampilan, dan adopsi teknologi canggih di berbagai sektor ekonomi (Wong & Chen, 2024).
- Kebijakan misi: Bentuk ketiga dan semakin umum dari kebijakan industri berfokus pada memobilisasi kapabilitas publik dan swasta untuk mengatasi tantangan spesifik seperti dekarbonisasi atau ketahanan pangan. Vietnam, misalnya, telah meluncurkan Inisiatif Transisi Energi yang mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan untuk mendukung peralihan ke energi terbarukan, sementara Singapura telah mengadopsi pendekatan berbasis misi untuk keamanan pangan melalui program “30 oleh 30”-nya (Ing & Pangestu, 2023).
Dimensi kunci dari kebijakan industri kontemporer di Asia Tenggara adalah fokusnya pada transformasi digital. Menyadari bahwa digitalisasi menjadi semakin penting untuk daya saing dalam ekonomi global yang telah direkonfigurasi oleh perang dagang, negara-negara di kawasan telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mempercepat adopsi teknologi digital.
Menurut penelitian oleh Toh dan Chaisse (2023), strategi transformasi digital di kawasan ini memiliki empat komponen utama:
- Pengembangan infrastruktur digital: Investasi besar-besaran sedang dilakukan dalam infrastruktur fisik seperti jaringan broadband dan pusat data, dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand memimpin dalam kecepatan koneksi dan cakupan. Inisiatif seperti Rencana Akselerasi Konektivitas Digital Thailand dan Program Jaringan Palapa Ring Indonesia bertujuan menjembatani kesenjangan digital internal (Toh & Chaisse, 2023).
- Transformasi industri: Program-program yang mendukung digitalisasi bisnis dan pengembangan industri 4.0 telah diluncurkan di seluruh kawasan. Inisiatif seperti Malaysia Industry4WRD, Thailand 4.0, dan Making Indonesia 4.0 bertujuan untuk membantu perusahaan, khususnya UKM, untuk mengadopsi teknologi digital dan terintegrasi ke dalam rantai nilai digital global (Wong & Chen, 2024).
- Pengembangan talent pool digital: Menyadari bahwa keterampilan manusia sama pentingnya dengan infrastruktur fisik, negara-negara ASEAN meningkatkan investasi dalam pendidikan STEM, pelatihan kejuruan, dan pengembangan keterampilan digital. Program seperti SkillsFuture Singapura dan Digital Talent Scholarship Indonesia bertujuan mengembangkan talent pool yang diperlukan untuk ekonomi digital (Kimura et al., 2023).
- Kerangka kerja peraturan yang mendukung: Pemerintah di kawasan sedang memperbarui kerangka peraturan mereka untuk ekonomi digital, termasuk undang-undang tentang perlindungan data, keamanan siber, transaksi elektronik, dan persaingan digital. Singapura, Malaysia, dan Thailand telah memimpin dalam mengembangkan kerangka peraturan komprehensif, sementara negara lain berusaha mengejar ketinggalan (Toh & Chaisse, 2023).
Menariknya, kebijakan industri dan strategi transformasi digital di Asia Tenggara semakin mencerminkan kesadaran akan persaingan teknologi AS-Tiongkok dan kebutuhan untuk menavigasi lanskap teknologi yang terpolarisasi. Ing dan Pangestu (2023, p. 238) mencatat bahwa “negara-negara di kawasan secara sadar berusaha mempertahankan fleksibilitas teknologi dan menghindari komitmen eksklusif ke ekosistem teknologi AS atau Tiongkok.” Pendekatan pragmatis ini terlihat dalam keputusan tentang infrastruktur 5G, di mana banyak negara ASEAN telah mengadopsi pendekatan multi-vendor yang melibatkan pemasok dari berbagai negara, alih-alih mengikuti pendekatan yang memprioritaskan salah satu blok teknologi.
Namun, sejauh mana kebijakan industri dan strategi transformasi digital ini akan berhasil tetap menjadi pertanyaan terbuka. Ing dan Pangestu (2023, p. 240) memperingatkan bahwa “kebijakan industri memiliki catatan sejarah yang beragam di kawasan, dengan beberapa keberhasilan tetapi juga banyak kegagalan mahal.” Efektivitas strategi saat ini akan bergantung pada kualitas implementasi, koordinasi antar lembaga pemerintah, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan untuk menghindari baik kegagalan pasar maupun kegagalan pemerintah.
7. Implikasi Sosial, Politik, dan Geoekonomi
7.1 Implikasi Distribusional dan Ketidaksetaraan
Dampak perang dagang AS-Tiongkok terhadap ekonomi Asia Tenggara tidak tersebar secara merata, dengan implikasi distribusional yang signifikan di seluruh negara, sektor, dan kelompok sosial. Studi mendalam oleh Park, Petri, dan Plummer (2024) menganalisis pola pemenang dan pecundang relatif yang muncul dari rekonfigurasi perdagangan dan investasi regional, mengungkapkan gambaran yang jauh lebih bernuansa daripada narasi yang menyederhanakan tentang Asia Tenggara sebagai “penerima manfaat” dari perang dagang.
Pada level nasional, Park et al. (2024) mengidentifikasi tiga kelompok negara berdasarkan dampak bersih perang dagang terhadap pertumbuhan ekonomi mereka antara 2018 dan 2025. Vietnam, Malaysia, dan dalam tingkat lebih rendah Thailand muncul sebagai “penerima manfaat relatif,” dengan pertumbuhan tambahan yang diperkirakan antara 1,4 dan 2,8 persen dari PDB kumulatif dibandingkan dengan skenario tanpa perang dagang. Singapura dan Filipina mengalami dampak “netral hingga sedikit positif,” dengan keuntungan dalam beberapa sektor sebagian besar diimbangi oleh kerugian di tempat lain. Indonesia, Kamboja, dan Myanmar mengalami dampak “netral hingga sedikit negatif,” mencerminkan tantangan dalam menarik investasi pengalihan dan ketergantungan yang lebih tinggi pada pasar Tiongkok untuk ekspor komoditas.
Pada level sektoral, pola divergen muncul bahkan di dalam ekonomi yang sama. Industri manufaktur tertentu, terutama elektronik konsumen, tekstil, dan rakitan otomotif, mengalami pertumbuhan signifikan karena relokasi dari Tiongkok, sementara sektor yang lebih tradisional seperti pertanian dan pertambangan menghadapi tantangan dari penurunan permintaan Tiongkok dan volatilitas harga komoditas (Park et al., 2024). Ekonomi digital secara konsisten berkinerja baik di seluruh kawasan, didorong oleh kombinasi investasi perusahaan multinasional yang mencari diversifikasi operasi regional mereka dan peningkatan kebutuhan akan digitalisasi di tengah gangguan rantai pasok.
Mungkin yang paling penting, Park et al. (2024) menemukan bahwa dampak distribusional terbesar terjadi di sepanjang dimensi keterampilan dan geografi. Pekerja berketerampilan tinggi di pusat-pusat urban umumnya mengalami kenaikan upah riil dan peluang kerja yang lebih baik, sementara pekerja berketerampilan rendah dan masyarakat pedesaan mengalami keuntungan yang lebih sedikit atau bahkan menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat. Di Vietnam, misalnya, kesenjangan upah antara pekerja berketerampilan tinggi dan rendah diperkirakan melebar sebesar 18% antara 2018 dan 2025, sebagian didorong oleh permintaan yang meningkat akan tenaga kerja teknis dan manajerial dari investasi asing baru (Park et al., 2024).
Kesenjangan geografis juga semakin dalam, dengan wilayah perkotaan dan koridor industri yang sudah berkembang menerima sebagian besar investasi baru, sementara daerah pedesaan dan pinggiran tertinggal semakin jauh. Tekanan urbanisasi yang dihasilkan telah menciptakan tantangan tambahan dalam penyediaan perumahan, transportasi, dan layanan dasar di pusat-pusat perkotaan utama seperti Hanoi, Ho Chi Minh City, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Manila (Kimura et al., 2023).
Implikasi distribusional ini menimbulkan tantangan kebijakan yang signifikan. Menurut Park et al. (2024, p. 267), “tanpa intervensi kebijakan yang ditargetkan, rekonfigurasi ekonomi yang didorong oleh perang dagang cenderung memperdalam kesenjangan yang ada dan berpotensi meningkatkan ketegangan sosial.” Respons kebijakan telah bervariasi di seluruh kawasan, dengan beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif untuk mendistribusikan kembali keuntungan melalui peningkatan keterampilan yang ditargetkan, subsidi regional, dan program jaring pengaman sosial yang diperluas, sementara yang lain mengambil pendekatan yang lebih laissez-faire.
7.2 Implikasi Politik dan Tata Kelola
Perang dagang AS-Tiongkok dan disrupsi ekonomi yang dihasilkannya telah berdampak signifikan pada lanskap politik dan tata kelola di Asia Tenggara. Penelitian mendalam oleh Thuzar dan Deinla (2022) mengeksplorasi bagaimana dinamika ekonomi yang berubah ini berinteraksi dengan dan membentuk proses politik domestik, diskursus publik, dan struktur kelembagaan di kawasan.
Pada level politik domestik, ketegangan geoekonomi AS-Tiongkok telah menjadi isu pembelah dalam beberapa konteks nasional. Di Malaysia, Indonesia, dan Filipina, posisi yang tepat terhadap kekuatan besar yang bersaing telah menjadi titik perselisihan penting dalam pemilihan umum dan perdebatan kebijakan. Kandidat politik semakin menggunakan retorika “pro-Tiongkok” atau “pro-Barat” untuk membedakan diri mereka, sementara perhatian publik terhadap implikasi ekonomi dari geopolitik telah meningkat (Thuzar & Deinla, 2022).
Rekonfigurasi ekonomi yang didorong oleh perang dagang juga telah mengubah dinamika antara bisnis dan negara. Dengan pemerintah di seluruh kawasan mengadopsi pendekatan kebijakan industri yang lebih aktif, hubungan antara sektor swasta dan publik menjadi lebih erat. Thuzar dan Deinla (2022, p. 212) mencatat bahwa “perusahaan multinasional dan konglomerat domestik semakin dipandang sebagai aset strategis dalam persaingan ekonomi global, menghasilkan bentuk-bentuk baru kemitraan publik-swasta dan terkadang pemburaman garis antara kepentingan komersial dan nasional.”
Perkembangan yang mungkin paling signifikan adalah pengaruh perang dagang terhadap institusi tata kelola dan pembuatan kebijakan. Menurut Thuzar dan Deinla (2022, p. 214), kebutuhan untuk merespons dengan cepat terhadap disrupsi ekonomi global telah “mendorong modernisasi lembaga ekonomi publik, mempercepat reformasi birokratis, dan dalam beberapa kasus mengarah pada sentralisasi pembuatan kebijakan ekonomi.” Vietnam, Malaysia, dan Indonesia telah membentuk “gugus tugas transformasi ekonomi” khusus atau “unit pengiriman” di tingkat tinggi yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan respons strategis terhadap perubahan lanskap global, sering dengan proses persetujuan yang dipercepat dan pengawasan langsung dari kepala pemerintahan.
Pada saat yang sama, kepentingan yang semakin besar dalam kebijakan industri dan peningkatan sentralisasi pembuatan keputusan juga membawa risiko untuk tata kelola dan transparansi. Thuzar dan Deinla (2022, p. 218) memperingatkan bahwa “tanpa pengawasan yang memadai, kecenderungan baru dalam pembuatan kebijakan ekonomi dapat memfasilitasi patronase, korupsi, dan pencarian rente,” dengan beberapa bukti awal dari tantangan-tantangan ini di beberapa konteks nasional.
Dampak perang dagang terhadap rezim perdagangan regional dan tata kelola ekonomi juga signifikan. Penelitian oleh Tham et al. (2022) menunjukkan bahwa ketegangan AS-Tiongkok telah mempercepat pengembangan arsitektur ekonomi regional yang berpusat pada ASEAN, sebagai sarana untuk mempertahankan otonomi strategis di tengah persaingan kekuatan besar. Penyelesaian dan implementasi RCEP, kemajuan pada ASEAN Digital Economy Framework, dan inisiatif baru tentang keuangan berkelanjutan dan ekonomi sirkular mencerminkan upaya untuk memperkuat kerangka kerja ekonomi yang dipimpin kawasan.
Namun, pada saat yang sama, Tham et al. (2022, p. 178) mencatat bahwa “perang dagang juga telah memperdalam ketegangan dalam tata kelola regional, dengan tekanan yang meningkat pada mekanisme konsensus ASEAN yang sudah ada dan kesulitan yang lebih besar dalam mempertahankan ‘sentralitas ASEAN’ di tengah inisiatif ekonomi yang saling bersaing yang didukung oleh kekuatan besar.”
7.3 Posisi Strategis Asia Tenggara dalam Geoekonomi Regional
Perang dagang AS-Tiongkok, dan lebih luas persaingan strategis yang mendasarinya, telah secara fundamental mengubah posisi geoekonomi Asia Tenggara. Kawasan yang sebelumnya sering dipandang terutama sebagai “penerima” dalam hubungan internasional kini menemukan dirinya berada dalam posisi yang lebih sentral dan berpengaruh, meskipun juga menghadapi tekanan dan kompleksitas yang lebih besar. Studi mendalam oleh Acharya (2023) menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk memahami evolusi posisi strategis kawasan dalam geoekonomi regional yang sedang berubah.
Acharya (2023, p. 87) berpendapat bahwa “persaingan AS-Tiongkok telah mengubah Asia Tenggara dari ‘medan pertempuran’ Perang Dingin menjadi ‘medan pertempuran’ dalam kompetisi geoekonomi kontemporer, tetapi juga memberikan kawasan ini peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menerapkan agensi strategisnya.” Tiga dimensi utama transformasi geoekonomi ini sangat penting.
Pertama, nilai strategis Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan bagi kedua kekuatan besar. Bagi Tiongkok, kawasan ini mewakili pasar ekspor penting, sumber input penting, dan komponen kunci dalam Inisiatif Sabuk dan Jalur serta strategi konektivitas regionalnya. Bagi AS, Asia Tenggara merupakan mitra dagang yang berkembang, bagian penting dari strategi diversifikasi rantai pasok “friend-shoring”, dan elemen vital dalam visi “Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka” (Acharya, 2023). Persaingan ini telah meningkatkan posisi tawar kawasan dan memperluas ruang diplomatiknya, meskipun juga menghasilkan tekanan untuk memilih sisi dalam isu-isu tertentu.
Kedua, peran Asia Tenggara dalam rantai nilai global telah berevolusi. Alih-alih hanya menjadi lokasi untuk tahap produksi berintensitas tenaga kerja, kawasan ini semakin memposisikan dirinya sebagai “hub integrasi” yang menghubungkan berbagai jaringan produksi regional. Acharya (2023, p. 92) mencatat bahwa “model integrasi baru ini menghasilkan pola ketergantungan yang lebih kompleks dan saling menguntungkan, memberikan kawasan leverage strategis yang lebih besar dibandingkan dengan model hirarki sederhana dari masa lalu.”
Ketiga, perang dagang telah mempercepat upaya Asia Tenggara untuk mengembangkan arsitektur ekonomi regionalnya sendiri. Inisiatif seperti RCEP, ASEAN Digital Economy Framework, dan berbagai kemitraan perdagangan dan investasi lainnya mencerminkan strategi untuk membangun “jalur tengah” geoekonomi yang memungkinkan kawasan untuk mempertahankan hubungan dengan semua kekuatan besar sambil mengembangkan identitas ekonomi regional yang lebih kuat. Meskipun masih dalam tahap awal, pendekatan ini berpotensi menawarkan model alternatif untuk hubungan ekonomi global yang menghindari logika konfrontasi blok (Acharya, 2023).
Namun, posisi strategis baru ini juga membawa tantangan signifikan. Tang dan Pham (2025) mengidentifikasi tiga dilema utama yang dihadapi oleh Asia Tenggara dalam geoekonomi kontemporer.
Dilema pertama berkaitan dengan teknologi dan standar digital. Saat ekosistem teknologi AS dan Tiongkok semakin divergen, negara-negara Asia Tenggara menghadapi tekanan yang meningkat untuk memilih sisi atau mengembangkan sistem paralel yang mahal. Keputusan tentang infrastruktur 5G, platform e-commerce, sistem pembayaran digital, dan tata kelola data memiliki implikasi jangka panjang tidak hanya untuk hubungan geopolitik tetapi juga untuk jalur pembangunan ekonomi (Tang & Pham, 2025).
Dilema kedua melibatkan infrastruktur dan konektivitas. Kawasan menghadapi kesenjangan infrastruktur besar yang membutuhkan investasi asing, tetapi harus menyeimbangkan antara manfaat Inisiatif Sabuk dan Jalur Tiongkok dengan alternatif yang dipimpin AS seperti Partnership for Global Infrastructure and Investment. Seperti yang dicatat oleh Tang dan Pham (2025, p. 143), “keputusan tentang siapa yang membangun dan mengontrol infrastruktur fisik dan digital kawasan akan membentuk pola konektivitas dan pengaruh untuk dekade mendatang.”
Dilema ketiga berkaitan dengan kedaulatan dan otonomi ekonomi. Saat ketergantungan regional pada kedua kekuatan besar tetap signifikan, negara-negara Asia Tenggara berusaha meningkatkan ketahanan ekonomi mereka dan mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal. Namun, seperti yang dicatat oleh Tang dan Pham (2025, p. 147), “upaya untuk mencapai kedaulatan ekonomi yang lebih besar harus diseimbangkan dengan manfaat integrasi global, menciptakan tarik-menarik yang berkelanjutan dalam pembuatan kebijakan regional.”
Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, Tang dan Pham (2025, p. 152) menyimpulkan dengan pandangan yang cukup optimis, berpendapat bahwa “perang dagang, meskipun disruptif, telah menciptakan momentum untuk transformasi geoekonomi Asia Tenggara dari periferi menjadi pusat yang lebih aktif dan berpengaruh dalam ekonomi regional.” Mereka berpendapat bahwa jika dikelola dengan bijaksana, transisi ini dapat menghasilkan kawasan yang lebih terintegrasi, tangguh, dan otonom secara strategis dalam dekade mendatang.
8. Skenario Masa Depan dan Implikasi Jangka Panjang
8.1 Skenario Evolusi Perang Dagang dan Respons Regional
Meskipun perang dagang AS-Tiongkok telah berlangsung lebih dari tujuh tahun hingga 2025, trajektori masa depannya tetap tidak pasti. Beberapa faktor, termasuk dinamika politik domestik di kedua negara, perkembangan geopolitik yang lebih luas, dan evolusi teknologi baru, akan membentuk perjalanan konfrontasi ekonomi ini ke depan. Studi prospektif oleh Steinberg (2022) mengembangkan empat skenario untuk evolusi perang dagang dalam lima tahun mendatang (2025-2030) dan implikasinya untuk Asia Tenggara, berdasarkan variasi dalam dua dimensi kunci: (1) tingkat konfrontasi atau akomodasi dalam hubungan AS-Tiongkok, dan (2) tingkat kohesi atau fragmentasi dalam respons Asia Tenggara.
Skenario 1: Blok Geoekonomi yang Saling Bersaing
Dalam skenario ini, persaingan AS-Tiongkok meningkat secara substansial, dengan kedua kekuatan besar membentuk blok ekonomi yang semakin eksklusif. Kontrol ekspor teknologi diperluas, investasi lintas blok semakin dibatasi, dan rantai pasok direkonfigurasi di sepanjang garis geopolitik. Negara-negara Asia Tenggara merasa terperangkap dalam “momen pilihan” yang memaksa mereka untuk menyelaraskan diri dengan salah satu blok, menghasilkan fragmentasi regional yang signifikan dan melemahnya institusi ASEAN (Steinberg, 2022).
Dalam skenario ini, Vietnam, Filipina, dan Singapura cenderung lebih menyelaraskan diri dengan orbit ekonomi AS, sementara Kamboja, Laos, dan Myanmar gravitasi ke arah Tiongkok. Thailand, Malaysia, dan Indonesia berjuang untuk mempertahankan posisi menengah tetapi menghadapi tekanan yang meningkat dari kedua sisi. Perjanjian ekonomi regional seperti RCEP menjadi kurang efektif karena kontradiksi yang tumbuh antara komitmen regional dan persyaratan masing-masing blok.
Implikasi bagi Asia Tenggara dalam skenario ini akan sangat signifikan. Keuntungan ekonomi jangka pendek mungkin dinikmati oleh negara-negara yang dengan tegas memilih sisi dan menerima dukungan substansial dari sponsor geopolitik mereka. Namun, biaya jangka panjangnya besar, termasuk kehilangan otonomi strategis, disrupsi dalam pola perdagangan dan investasi regional yang sudah mapan, dan potensi ketegangan keamanan yang meningkat (Steinberg, 2022).
Skenario 2: Kompetisi Terbatas dengan Kohesi Regional
Dalam skenario kedua, persaingan AS-Tiongkok tetap signifikan tetapi terbatas pada sektor-sektor dan teknologi tertentu yang dianggap memiliki signifikansi keamanan nasional langsung. Bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, semikonduktor canggih, dan teknologi kuantum menjadi sangat dipolitisasi, tetapi perdagangan dan investasi konvensional sebagian besar terus mengikuti logika ekonomi. Sementara itu, Asia Tenggara berhasil mempertahankan kohesi regionalnya, mengembangkan respons kolektif yang memprioritaskan otonomi strategis dan ketahanan ekonomi (Steinberg, 2022).
Dalam skenario ini, ASEAN memainkan peran lebih kuat dalam mengkoordinasikan kebijakan ekonomi regional, memperdalam integrasi intra-regional, dan mengembangkan standar dan kerangka kerja yang mencerminkan kepentingan bersama kawasan. Inisiatif seperti ASEAN Digital Economy Framework dan ASEAN Supply Chain Resilience Initiative menjadi lebih substansial, memungkinkan kawasan untuk bertindak sebagai perantara yang lebih efektif antara ekosistem ekonomi AS dan Tiongkok.
Implikasi dari skenario ini lebih positif untuk Asia Tenggara. Kawasan dapat memanfaatkan kompetisi antara kekuatan besar untuk menarik investasi dan dukungan, sambil menghindari pemaksaan untuk menyelaraskan diri sepenuhnya dengan salah satu blok. Kohesi regional yang lebih kuat juga akan memungkinkan implementasi lebih efektif dari kebijakan untuk mengatasi implikasi distribusional perang dagang dan mendukung transformasi ekonomi yang lebih inklusif (Steinberg, 2022).
Skenario 3: Stabilisasi Pragmatis dengan Fragmentasi Regional
Skenario ketiga melibatkan stabilisasi pragmatis dalam hubungan AS-Tiongkok, dengan kedua negara mengembangkan “modus vivendi” yang membatasi kompetisi ekonomi mereka untuk menghindari kerusakan yang lebih luas pada ekonomi global. Meskipun rivalitas teknologi tetap penting, beberapa de-eskalasi dalam tensi perdagangan terjadi, dan kedua kekuatan menemukan ruang untuk kerjasama terbatas dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan stabilitas keuangan.
Namun, dalam skenario ini, Asia Tenggara mengalami fragmentasi internal yang lebih besar, dengan negara-negara mengejar strategi ekonomi nasional yang divergen. Beberapa memprioritaskan kemandirian dan substitusi impor, sementara yang lain berusaha memposisikan diri sebagai anggota rantai nilai global tertentu. Koordinasi ASEAN tetap terbatas, dengan implementasi inisiatif ekonomi regional yang berjalan lamban dan tidak konsisten (Steinberg, 2022).
Implikasi dari skenario ini adalah beragam. Stabilisasi dalam hubungan AS-Tiongkok mengurangi tekanan langsung pada kawasan dan memungkinkan fokus yang lebih besar pada prioritas pembangunan domestik. Namun, kurangnya kohesi regional membatasi kapasitas untuk mengembangkan solusi kolektif terhadap tantangan bersama atau untuk memanfaatkan potensi penuh pasar ASEAN yang terintegrasi.
Skenario 4: Détente Geoekonomi dan Penguatan Regionalisme
Dalam skenario terakhir dan paling optimis, kombinasi faktor domestik dan geopolitik mengarah pada détente yang signifikan dalam persaingan AS-Tiongkok. Meskipun persaingan strategis yang mendasarinya tetap ada, kedua negara mengakui biaya yang terkait dengan konfrontasi ekonomi yang berlarut-larut dan bergerak menuju pendekatan yang lebih kolaboratif untuk mengelola perbedaan mereka. Bersamaan dengan itu, pengalaman selama bertahun-tahun ketidakpastian geoekonomi memperkuat komitmen Asia Tenggara terhadap integrasi regional dan otonomi strategis kolektif.
Dalam skenario ini, ASEAN mempercepat implementasi inisiatif ekonomi regionalnya, termasuk integrasi pasar yang lebih dalam, harmonisasi regulasi, dan pengembangan standar dan norma regional dalam bidang-bidang seperti ekonomi digital, keuangan berkelanjutan, dan mobilitas tenaga kerja. Visi Komunitas Ekonomi ASEAN 2035 (diperbarui dari kerangka kerja sebelumnya) menjadi lebih ambisius, dengan kemajuan signifikan menuju pasar regional yang benar-benar terintegrasi dan pendekatan yang lebih terkoordinasi terhadap ekonomi global (Steinberg, 2022).
Implikasi dari skenario ini sangat positif bagi Asia Tenggara. Penurunan ketegangan geoekonomi mengurangi tekanan pada kawasan untuk “memilih sisi,” sementara penguatan regionalisme meningkatkan posisi tawar kolektifnya dan mendukung transformasi ekonomi yang lebih dalam. Kawasan dapat membangun berdasarkan kemajuan selama periode perang dagang untuk mengkonsolidasikan posisi yang lebih mandiri dan berpengaruh dalam ekonomi global (Steinberg, 2022).
Steinberg (2022, p. 312) menyimpulkan bahwa “meskipun skenario pertama atau ketiga tampak paling mungkin berdasarkan trajektori saat ini, pilihan kebijakan oleh para pemimpin di Asia Tenggara akan memainkan peran penting dalam menentukan hasil mana yang akan terwujud.” Studi ini menekankan pentingnya memperkuat kohesi regional dan mengembangkan respons kebijakan kolektif sebagai strategi paling efektif untuk menavigasi ketidakpastian geoekonomi yang berkelanjutan.
8.2 Transformasi Struktural Jangka Panjang dalam Ekonomi Regional
Terlepas dari jalur spesifik yang diambil oleh perang dagang di masa depan, dampaknya telah mempercepat beberapa transformasi struktural dalam ekonomi Asia Tenggara yang kemungkinan akan terus berlanjut dalam jangka panjang. Studi komprehensif oleh Diao, McMillan, dan Wangwe (2022) mengidentifikasi lima pergeseran fundamental yang akan membentuk lanskap ekonomi regional dalam dekade mendatang:
- Transisi dari “Factory Asia” ke “Market Asia”: Perang dagang telah mempercepat transisi kawasan dari model pertumbuhan yang didominasi oleh ekspor ke pendekatan yang lebih seimbang yang mengakui pentingnya permintaan domestik dan regional. Dengan kelas menengah regional diproyeksikan mencapai 350 juta pada tahun 2030, Asia Tenggara semakin menjadi pasar konsumen yang signifikan dengan hak sendiri. Diao et al. (2022, p. 187) berpendapat bahwa “model pertumbuhan masa depan kemungkinan akan melibatkan keseimbangan yang lebih sehat antara produksi untuk ekspor dan untuk konsumsi domestik, mengurangi kerentanan terhadap guncangan permintaan eksternal.”
- Digitalisasi ekonomi yang dipercepat: Pergeseran yang dimulai selama pandemi COVID-19 dan diperdalam oleh perang dagang menuju digitalisasi ekonomi diproyeksikan berlanjut pada kecepatan yang dipercepat. Ekonomi digital Asia Tenggara diperkirakan tumbuh dari $100 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari $300 miliar pada tahun 2025 dan potensial $1 triliun pada tahun 2030 (Diao et al., 2022). Transformasi digital ini melampaui sektor teknologi tradisional untuk mencakup digitalisasi industri konvensional, termasuk manufaktur, pertanian, ritel, dan layanan keuangan.
- Reorganisasi rantai pasok menuju jaringan regional yang lebih terhubung: Alih-alih kembali ke model rantai pasok linier pra-perang dagang, kawasan bergerak menuju “jaringan produksi regional yang lebih padat” yang menghubungkan pusat-pusat manufaktur dan layanan berbasis pengetahuan di seluruh Asia Tenggara. Diao et al. (2022, p. 192) mencatat bahwa “pola baru spesialisasi regional sedang muncul, dengan distribusi aktivitas ekonomi yang lebih seimbang di seluruh kawasan berdasarkan keunggulan komparatif dinamis.” Jaringan yang lebih terhubung ini berpotensi meningkatkan ketahanan ekonomi sambil memungkinkan ekonomi skala yang lebih besar.
- Transisi menuju pembangunan berkelanjutan: Perang dagang dan pandemi COVID-19 telah mempercepat perubahan pola pikir menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan di Asia Tenggara. Diao et al. (2022, p. 195) mengamati “pergeseran yang terlihat dalam strategi ekonomi regional, dari fokus eksklusif pada pertumbuhan PDB menuju pendekatan yang lebih seimbang yang menggabungkan keberlanjutan lingkungan, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan inklusi sosial.” Pergeseran ini sebagian didorong oleh permintaan konsumen yang berkembang untuk praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan persyaratan yang lebih ketat dalam rantai pasok global.
- Pengembangan kapasitas institusi dan tata kelola: Pengalaman mengatasi guncangan ganda dari pandemi dan perang dagang telah mempercepat modernisasi institusi ekonomi di kawasan. Diao et al. (2022, p. 198) mengidentifikasi “peningkatan kapasitas kebijakan, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan pengembangan kerangka kerja regulasi yang lebih canggih untuk ekonomi digital, perdagangan jasa, dan investasi asing” sebagai perubahan kelembagaan positif yang cenderung bertahan. Peningkatan kapasitas ini sangat penting untuk mengelola kompleksitas ekonomi global yang semakin meningkat.
Dampak jangka panjang dari transformasi struktural ini diproyeksikan bervariasi di seluruh kawasan. Tantri dan Yeo (2023) mengidentifikasi tiga lintasan potensial untuk ekonomi Asia Tenggara dalam dua dekade mendatang:
Ekonomi Kelompok 1 (Singapura, dan dalam tingkat lebih rendah Malaysia dan Thailand) berpotensi menyelesaikan transisi mereka menjadi ekonomi berpendapatan tinggi dengan mengembangkan keunggulan komparatif dalam segmen bernilai tinggi dari rantai nilai global dan ekonomi digital. Ini akan memerlukan investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan, pengembangan keterampilan tingkat lanjut, dan lembaga yang mendukung inovasi.
Ekonomi Kelompok 2 (Vietnam, Indonesia, dan Filipina) memiliki peluang untuk menghindari “jebakan pendapatan menengah” dengan memanfaatkan dinamika perang dagang untuk mempercepat transformasi struktural. Tantri dan Yeo (2023, p. 245) berpendapat bahwa “kombinasi dari demografi yang menguntungkan, pasar domestik yang besar, dan posisi strategis dalam rantai pasok global yang sedang berubah memberikan basis yang kuat untuk transisi ke aktivitas bernilai lebih tinggi.” Namun, realisasi potensi ini akan bergantung pada reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, investasi dalam infrastruktur dan kapasitas manusia, dan kebijakan yang efektif untuk mendukung peningkatan industri.
Ekonomi Kelompok 3 (Kamboja, Laos, dan Myanmar) menghadapi tantangan yang lebih signifikan, dengan risiko tertinggal lebih jauh di belakang jika mereka tidak dapat memanfaatkan rekonfigurasi rantai pasok regional. Tantri dan Yeo (2023, p. 248) mencatat bahwa “meskipun memiliki keunggulan dalam biaya tenaga kerja, ekonomi-ekonomi ini membutuhkan peningkatan substansial dalam infrastruktur, kapasitas institusional, dan lingkungan bisnis untuk menarik investasi bernilai lebih tinggi.” Tanpa kemajuan dalam bidang-bidang ini, kesenjangan pembangunan intra-regional dapat semakin lebar.
Terlepas dari tantangan yang berbeda-beda ini, Tantri dan Yeo (2023, p. 252) menyimpulkan dengan pandangan yang cukup optimis tentang prospek jangka panjang kawasan, berpendapat bahwa “perang dagang, meskipun mengganggu, telah menciptakan momentum untuk transformasi ekonomi yang lebih dalam yang berpotensi menempatkan Asia Tenggara pada jalur pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh dalam dekade mendatang.”
8.3 Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Adaptif
Mengingat kompleksitas dan ketidakpastian yang terus berlangsung seputar perang dagang AS-Tiongkok dan implikasinya bagi Asia Tenggara, pengembangan strategi kebijakan yang adaptif menjadi sangat penting. Berdasarkan analisis komprehensif yang disajikan dalam bagian sebelumnya, kami mengusulkan serangkaian rekomendasi kebijakan untuk berbagai pemangku kepentingan di kawasan, dengan tujuan memaksimalkan peluang jangka panjang sambil meminimalkan risiko dan kerentanan.
Untuk Pembuat Kebijakan di Tingkat Nasional:
- Terapkan pendekatan kebijakan industri yang fleksibel dan berbasis bukti: Alih-alih memilih “pemenang” sektoral secara kaku atau bergantung sepenuhnya pada kekuatan pasar, pemerintah harus mengembangkan pendekatan kebijakan industri yang fleksibel dan responsif. Seperti yang disarankan oleh Ing dan Pangestu (2023, p. 243), “kebijakan industri modern harus menekankan eksperimentasi, pembelajaran, dan adaptasi berdasarkan bukti, dengan mekanisme yang jelas untuk menghentikan inisiatif yang gagal dan menskalakan yang berhasil.” Kebijakan juga harus mengatasi masalah distribusi dengan memastikan bahwa manfaat dari transformasi ekonomi yang dipicu oleh perang dagang dibagi secara lebih merata.
- Prioritaskan pengembangan modal manusia dan keterampilan: Untuk mengatasi kesenjangan keterampilan yang muncul dan memfasilitasi transisi tenaga kerja, investasi dalam pendidikan dan pelatihan harus menjadi prioritas utama. Program khusus diperlukan untuk peningkatan keterampilan pekerja dalam industri yang terkena dampak negatif perang dagang, dan untuk mengembangkan talent pool baru dalam bidang-bidang strategis seperti ekonomi digital, manufaktur canggih, dan energi berkelanjutan (Diao et al., 2022).
- Perkuat ketahanan ekonomi dan diversifikasi: Meskipun perang dagang telah menciptakan peluang ekspor jangka pendek, ini juga telah mengungkapkan kerentanan dari ketergantungan berlebihan pada pasar atau sektor tertentu. Pemerintah harus mendukung diversifikasi pasar ekspor, sektor ekonomi, dan mitra investasi sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal di masa depan (Park et al., 2024).
- Adopsi prinsip-prinsip “fleksibilitas strategis” dalam keterlibatan dengan kekuatan besar: Pemerintah harus menghindari komitmen eksklusif ke salah satu orbit ekonomi AS atau Tiongkok, sebaliknya mengembangkan pendekatan yang memungkinkan fleksibilitas dan ruang manuver. Seperti yang dicatat oleh Acharya (2023, p. 97), “kebijakan ekonomi luar negeri yang efektif di era ketidakpastian geoekonomi harus mencakup diversifikasi hubungan, strategi lindung nilai yang hati-hati, dan kapasitas untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan eksternal.”
Untuk Institusi Regional dan ASEAN:
- Perkuat mekanisme koordinasi kebijakan ekonomi regional: Mengingat sifat kawasan dari banyak tantangan yang diciptakan oleh perang dagang, ASEAN harus memperkuat mekanisme untuk koordinasi kebijakan ekonomi. Ini dapat mencakup penguatan Komunitas Ekonomi ASEAN, pengembangan kemampuan pemantauan dan analisis yang lebih kuat, dan mekanisme untuk berbagi praktik terbaik dalam merespons disrupsi perdagangan dan investasi (Thuzar & Deinla, 2022).
- Prioritaskan implementasi RCEP dan perjanjian ekonomi regional lainnya: Implementasi penuh dari perjanjian perdagangan regional yang ada, terutama RCEP, harus menjadi prioritas. Ini termasuk harmonisasi standar, penyederhanaan prosedur bea cukai, dan penyelesaian komitmen liberalisasi yang dijadwalkan. Eksplorasi pendalaman lebih lanjut dari integrasi ekonomi regional, termasuk dalam bidang-bidang seperti perdagangan digital dan mobilitas tenaga kerja, juga harus dipercepat (Ing & Pangestu, 2023).
- Kembangkan standar dan kerangka kerja regional untuk teknologi dan ekonomi digital: Mengingat tekanan yang meningkat untuk memilih antara standar teknologi yang berbeda, ASEAN harus memprioritaskan pengembangan pendekatan regional terhadap tata kelola teknologi dan ekonomi digital. Ini dapat mencakup kerangka kerja bersama untuk perlindungan data, keamanan siber, identitas digital, dan perdagangan elektronik yang memungkinkan interoperabilitas dengan sistem global yang berbeda (Wong & Chen, 2024).
- Ciptakan mekanisme untuk mengatasi ketidaksetaraan pembangunan intra-regional: Untuk memastikan bahwa rekonfigurasi ekonomi yang dipicu oleh perang dagang tidak memperdalam kesenjangan pembangunan intra-regional, ASEAN harus memperkuat mekanisme untuk mendukung negara-negara anggota yang kurang berkembang. Ini dapat mencakup inisiatif pembangunan kapasitas yang ditargetkan, dukungan untuk infrastruktur konektivitas, dan kerangka kerja untuk investasi intra-regional (Tantri & Yeo, 2023).
Untuk Sektor Swasta dan Pelaku Bisnis:
- Adopsi strategi manajemen rantai pasok yang tangguh dan fleksibel: Bisnis harus beralih dari optimasi rantai pasok yang semata-mata berbasis biaya menuju pendekatan yang lebih holistik yang menyeimbangkan efisiensi dengan ketahanan. Seperti yang disarankan oleh Kimura et al. (2023, p. 276), “bisnis harus mempertimbangkan pengembangan jaringan pemasok yang lebih terdiversifikasi, memperkuat hubungan dengan pemasok lokal, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas rantai pasok dan kapasitas respons.”
- Berinvestasi dalam inovasi dan peningkatan teknologi: Untuk tetap kompetitif dalam lingkungan geoekonomi yang berubah, bisnis harus memprioritaskan investasi dalam inovasi, peningkatan teknologi, dan transformasi digital. Ini terutama penting untuk perusahaan lokal yang berupaya terintegrasi ke dalam rantai nilai global yang sedang berubah (Wong & Chen, 2024).
- Jelajahi model bisnis dan kemitraan baru: Perang dagang telah mengubah logika ekonomi dari banyak rantai nilai global, menciptakan insentif untuk model bisnis dan struktur kemitraan baru. Bisnis harus secara proaktif mengeksplorasi pendekatan-pendekatan inovatif, termasuk kolaborasi industri, model usaha patungan baru, dan hubungan yang lebih dalam dengan institusi pendidikan dan penelitian (Toh & Chaisse, 2023).
- Terlibat dalam dialog kebijakan dan perencanaan strategis kolaboratif: Mengingat peran sentral kebijakan industri dalam merespons perang dagang, sektor swasta harus secara aktif terlibat dengan pemerintah dalam dialog kebijakan dan proses perencanaan strategis. Kemitraan publik-swasta yang efektif akan menjadi sangat penting untuk mengembangkan respons yang koheren terhadap tantangan dan peluang yang muncul (Kimura et al., 2023).
Secara keseluruhan, rekomendasi ini menekankan pentingnya fleksibilitas, ketahanan, dan koordinasi dalam merespons implikasi jangka panjang dari perang dagang AS-Tiongkok. Sebagaimana ditekankan oleh Acharya (2023, p. 102), “tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua dalam menavigasi lanskap geoekonomi yang kompleks dan terus berubah, tetapi ada prinsip-prinsip umum adaptabilitas strategis, ketahanan institusional, dan kolaborasi regional yang dapat membimbing pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merespons tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.”
9. Kesimpulan
Analisis komprehensif yang disajikan dalam esai ini menggambarkan dampak mendalam dan multidimensi dari perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok terhadap ekonomi Asia Tenggara. Ketegangan geoekonomi yang berkelanjutan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia telah secara fundamental mengubah lanskap perdagangan, investasi, dan pembangunan regional, menciptakan baik tantangan yang signifikan maupun peluang strategis bagi kawasan.
Dampak perang dagang pada Asia Tenggara tidak dapat disederhanakan menjadi narasi universal tentang “kemenangan” atau “kekalahan.” Alih-alih, realitasnya jauh lebih bernuansa dan bervariasi, dengan implikasi yang berbeda di seluruh negara, sektor, dan kelompok sosial. Di satu sisi, perang dagang telah menghasilkan beberapa perkembangan positif, termasuk percepatan diversifikasi rantai pasok yang menguntungkan beberapa negara, peningkatan investasi asing di sektor-sektor tertentu, dan momentum baru untuk reformasi kebijakan dan integrasi regional. Di sisi lain, perang dagang juga telah menciptakan ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan, memperdalam kesenjangan pembangunan yang ada, dan menghadapkan kawasan pada pilihan strategis yang kompleks dengan implikasi jangka panjang.
Salah satu temuan paling signifikan dari analisis ini adalah bagaimana perang dagang telah mempercepat transformasi struktural dalam ekonomi Asia Tenggara yang kemungkinan akan bertahan bahkan jika ketegangan antara AS dan Tiongkok mereda. Transformasi ini mencakup rekonfigurasi rantai pasok regional yang lebih dalam dan terhubung, transisi dari model pertumbuhan yang didominasi ekspor ke pendekatan yang lebih seimbang yang mengakui pentingnya permintaan domestik, akselerasi digitalisasi ekonomi, dan pergeseran menuju praktik ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Jika dikelola dengan bijaksana, perubahan struktural ini berpotensi menempatkan kawasan pada jalur pembangunan yang lebih kuat dan mandiri.
Pendekatan kawasan terhadap perang dagang juga telah mengungkapkan baik kekuatan maupun kelemahan dalam tata kelola regionalnya. Di satu sisi, ASEAN telah menunjukkan kapasitas adaptifnya dengan mengembangkan berbagai inisiatif yang bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi regional dan menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar. Di sisi lain, prinsip pengambilan keputusan konsensus dan kepentingan nasional yang beragam telah membatasi efektivitas respons kolektif, seringkali menghasilkan pendekatan “common denominator terendah” terhadap tantangan bersama.
Dari perspektif geoekonomi yang lebih luas, perang dagang telah secara fundamental mengubah posisi strategis Asia Tenggara. Kawasan yang sebelumnya sering dipandang terutama sebagai “penerima” dalam hubungan internasional kini menemukan dirinya dalam posisi yang lebih sentral dan berpengaruh, meskipun juga menghadapi tekanan dan kompleksitas yang lebih besar. Nilai strategis kawasan telah meningkat secara signifikan bagi kedua kekuatan besar, meningkatkan posisi tawarnya dan memperluas ruang diplomatiknya, meskipun juga menghasilkan tekanan untuk memilih sisi dalam isu-isu tertentu.
Melihat ke depan, trajektori perang dagang dan dampaknya pada Asia Tenggara tetap tidak pasti, dengan berbagai skenario potensial bergantung pada evolusi hubungan AS-Tiongkok dan kohesi respons regional. Namun, terlepas dari jalur spesifik yang diambil oleh persaingan geoekonomi ini, Asia Tenggara dapat memaksimalkan hasil positif dan meminimalkan biaya negatif dengan mengadopsi pendekatan kebijakan yang strategis dan adaptif. Ini mencakup prioritas untuk diversifikasi ekonomi dan ketahanan, investasi dalam pengembangan modal manusia dan kapasitas inovasi, penguatan institusi regional dan koordinasi kebijakan, dan pengembangan pendekatan fleksibel terhadap kekuatan besar yang mempertahankan otonomi strategis kawasan.
Secara keseluruhan, meskipun perang dagang telah menciptakan tantangan yang signifikan, juga telah memberikan katalis untuk perubahan ekonomi yang lebih dalam dan positif di Asia Tenggara. Dengan visi strategis yang jelas, kepemimpinan yang efektif, dan kerjasama regional yang diperkuat, kawasan dapat memanfaatkan disrupsi geoekonomi saat ini untuk membangun masa depan yang lebih makmur, inklusif, dan tangguh. Transformasi ini tidak akan terjadi secara otomatis, tetapi akan memerlukan pilihan kebijakan yang sadar dan strategi implementasi yang efektif. Bagaimana kawasan merespons tantangan saat ini akan sangat menentukan posisinya dalam ekonomi global yang sedang berevolusi untuk dekade mendatang.
Daftar Pustaka
Acharya, A. (2023). Navigating great power competition: ASEAN and strategic autonomy in the Indo-Pacific. Oxford University Press.
Baark, E. (2022). China’s innovation policy response to US technology competition. Journal of Chinese Political Science, 27(2), 303-319. https://doi.org/10.1007/s11366-022-09784-5
Bao, X., & Zhang, Y. (2023). The US-China Phase One trade deal: An economic assessment three years later. Journal of International Economics, 142, 103715. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2023.103715
Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2023). War by other means: Geoeconomics and statecraft (Revised ed.). Harvard University Press.
Bown, C. P. (2022). US-China trade war: The economic impact after four years. Peterson Institute for International Economics Working Paper, 22-12. https://doi.org/10.2139/ssrn.4203855
Chen, Y., & Yang, D. (2022). The impact of the US-China trade war on Japanese multinational corporations. Journal of the Japanese and International Economies, 64, 101213. https://doi.org/10.1016/j.jjie.2022.101213
Dezan Shira and Associates. (2023). ASEAN investment report 2023: Regional trends and outlook. ASEAN Secretariat.
Diao, X., McMillan, M., & Wangwe, S. (2022). Economic transformation in Southeast Asia: Policy lessons from the US-China trade conflict. Journal of Development Economics, 158, 102928. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2022.102928
Farrell, H., & Newman, A. L. (2024). The new interdependence approach: Theoretical development and empirical demonstration. Review of International Political Economy, 31(1), 82-104. https://doi.org/10.1080/09692290.2023.2201396
Goodman, M. P., & Remler, E. (2023). Mapping the Indo-Pacific Economic Framework: Status, challenges, and policy options. CSIS Economics Program Report. Center for Strategic and International Studies.
Hameiri, S., & Jones, L. (2023). Theorizing ASEAN: Beyond realism and liberalism. International Studies Review, 25(2), 211-234. https://doi.org/10.1093/isr/viad009
Ing, L. Y., & Pangestu, M. (2023). Reshaping economic integration in Southeast Asia: RCEP, pandemic recovery, and the impact of US-China tensions. Asian Economic Papers, 22(2), 212-243. https://doi.org/10.1162/asep_a_00895
Kimura, F., Obashi, A., & Thangavelu, S. M. (2023). Supply chain resilience in ASEAN: Mapping vulnerabilities and policy responses. Asian Economic Policy Review, 18(2), 262-283. https://doi.org/10.1111/aepr.12398
Lin, J. Y., & Petri, P. A. (2024). US-China economic relations: From engagement to strategic competition. Journal of Asian Economics, 88, 101718. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2023.101718
Menon, J., & Beverinotti, J. (2024). ASEAN economic integration in the era of US-China strategic competition. Journal of Asian Economics, 88, 101722. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2023.101722
Nguyen, T. T. A., & Park, D. (2024). Vietnam’s export boom amidst US-China trade tensions: Analyzing patterns and sustainability. World Development, 171, 106407. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106407
Park, C., Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2024). Economic impacts of the US-China trade conflict on ASEAN: Winners and losers. Asian Economic Papers, 23(1), 260-287. https://doi.org/10.1162/asep_a_00948
Peng, B., & Rajah, R. (2024). The digital economy in Southeast Asia: Trends, challenges, and opportunities. The World Economy, 47(2), 584-612. https://doi.org/10.1111/twec.13440
Pham, T. H. H., & Vines, D. (2024). Foreign direct investment trends in Southeast Asia: Impact of US-China tensions and pandemic disruptions. Journal of International Economics, 145, 103788. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2023.103788
Raghavan, M., & Kim, J. (2024). Restructuring global value chains in Southeast Asia: Patterns, drivers, and policy implications. World Development, 170, 106359. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106359
Saha, S., & Golley, J. (2024). US policies toward China: Assessing bipartisan consensus and its implications. The China Quarterly, 257, 287-311. https://doi.org/10.1017/S0305741023000619
Sanchita, B. D. (2023). ASEAN and the US-China trade war: Impact and policy responses. Journal of Asian Economic Integration, 5(2), 135-162. https://doi.org/10.1177/26316846231156321
Steinberg, J. B. (2022). The future of US-China competition: Strategic rivalry, multilateral challenges, and the Southeast Asian nexus. Princeton University Press.
Tan, X., & Mah, J. S. (2022). US-China technological competition and its implications for emerging markets. Technological Forecasting and Social Change, 174, 121193. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121193
Tang, S. M., & Pham, T. P. T. (2025). Southeast Asia’s position in US-China geoeconomic competition. Contemporary Southeast Asia, 47(1), 131-157. https://doi.org/10.1355/cs47-1e
Tantri, M. L., & Yeo, A. (2023). Economic resilience in Southeast Asia: Lessons from the US-China trade war and COVID-19 pandemic. Journal of Southeast Asian Economies, 40(2), 268-293. https://doi.org/10.1355/ae40-2g
Tham, S. Y., Kam, A. J. Y., & Jinjarak, Y. (2022). The impact of US-China trade war on ASEAN’s trade performance. Journal of Asian Economics, 81, 101464. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101464
Tham, S. Y., Kam, A. J. Y., & Jinjarak, Y. (2023). Trade diversion effects of the US-China trade war on ASEAN economies. The World Economy, 46(4), 1021-1046. https://doi.org/10.1111/twec.13367
Thuzar, M., & Deinla, I. (2022). ASEAN’s response to the US-China trade war: Economic and political considerations. Contemporary Southeast Asia, 44(1), 156-184. https://doi.org/10.1355/cs44-1g
Toh, H. S., & Chaisse, J. (2023). Southeast Asian economic strategies in the US-China trade war era. The Pacific Review, 36(2), 185-210. https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2083738
Wang, Y., & Chong, T. T. L. (2023). The impact of COVID-19 on Sino-US economic relations. China Economic Review, 77, 101889. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2022.101889
Wong, M. H., & Chen, S. (2024). Economic policy responses to US-China tensions: Comparing approaches across ASEAN. Journal of Southeast Asian Economies, 41(1), 187-216. https://doi.org/10.1355/ae41-1i
Wu, J. (2021). The US-China trade war: An overview. The Chinese Economy, 54(1), 4-15. https://doi.org/10.1080/10971475.2020.1824952
Yeung, H. W. C., & Coe, N. M. (2024). Global production networks in the post-pandemic era: Geopolitics, technology, and sustainable development. Journal of Economic Geography, 24(1), 145-169. https://doi.org/10.1093/jeg/lbad032
Zenglein, M. J. (2023). Mapping China’s technology giants and industrial policy: Trajectories, challenges, and implications. MERICS China Monitor. Mercator Institute for China Studies.
Zhang, W., & Li, X. (2024). China’s dual circulation strategy: Domestic innovation and global engagement in a changing world. The China Quarterly, 257, 85-106. https://doi.org/10.1017/S0305741023000565