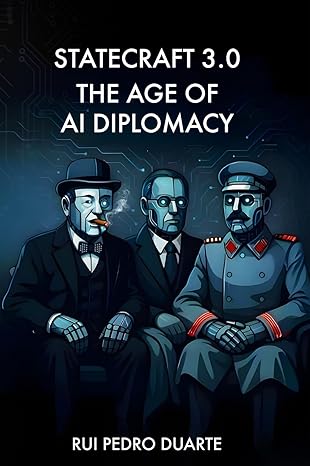
Oleh
Dr. Asep Setiawan
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Pendahuluan
Dalam era digital yang berkembang pesat, transformasi teknologi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk praktik diplomasi dan hubungan internasional. Buku Statecraft 3.0: The Age of AI Diplomacy karya Rui Duarte hadir sebagai kontribusi penting dalam memahami bagaimana kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah merevolusi lanskap diplomasi global. Duarte, seorang diplomat dan peneliti yang memiliki pengalaman luas dalam bidang teknologi dan kebijakan internasional, menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana AI tidak hanya mengubah cara negara-negara berinteraksi, tetapi juga mendefinisikan ulang esensi dari kekuasaan dan pengaruh dalam tatanan global kontemporer.
Diplomasi, sebagai seni dan praktik mengelola hubungan internasional, telah mengalami beberapa fase evolusi sepanjang sejarah. Dari diplomasi tradisional yang mengandalkan pertemuan tatap muka dan korespondensi tertulis, berkembang menjadi diplomasi publik yang memanfaatkan media massa, hingga kini memasuki era diplomasi digital yang didukung oleh teknologi canggih. Duarte berpendapat bahwa kita sedang berada di ambang fase baru yang ia sebut sebagai “Statecraft 3.0”, di mana AI bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan aktor yang memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan diplomatik dan strategis (Duarte, 2023). Konsep ini sejalan dengan pandangan Bjola dan Holmes (2015) yang mengidentifikasi bahwa digitalisasi telah mengubah struktur fundamental dari praktik diplomasi, menciptakan apa yang mereka sebut sebagai “digital diplomacy” yang menuntut adaptasi cepat dari para praktisi hubungan internasional.
Relevansi buku ini semakin mendesak ketika kita menyaksikan bagaimana negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara Uni Eropa berlomba-lomba mengembangkan kapabilitas AI untuk kepentingan keamanan nasional dan strategi geopolitik mereka. Horowitz (2018) mencatat bahwa kompetisi AI telah menjadi dimensi baru dari rivalitas kekuatan besar, menciptakan dinamika yang kompleks dalam sistem internasional. Dalam konteks ini, Duarte menawarkan perspektif yang seimbang dan komprehensif tentang peluang dan tantangan yang muncul dari fenomena ini, menjadikan karyanya sebagai bacaan yang esensial bagi akademisi, diplomat, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tertarik memahami masa depan hubungan internasional.
Garis Besar
Buku Statecraft 3.0: The Age of AI Diplomacy disusun secara sistematis dalam beberapa bagian yang saling terkait, membentuk narasi koheren tentang transformasi diplomasi di era AI. Duarte memulai dengan meletakkan fondasi konseptual yang kuat sebelum bergerak ke analisis aplikasi praktis dan implikasi kebijakan dari fenomena yang ia kaji. Struktur buku ini menunjukkan pemahaman mendalam penulis tentang kebutuhan untuk menjembatani teori dan praktik dalam diskusi tentang teknologi dan hubungan internasional.
Bagian pertama buku ini berfokus pada evolusi konsep statecraft dari masa ke masa. Duarte (2023) menjelaskan bahwa statecraft tradisional (1.0) berpusat pada diplomasi bilateral dan multilateral yang konvensional, di mana negosiasi tatap muka dan perjanjian formal menjadi instrumen utama. Transisi ke statecraft 2.0 ditandai oleh munculnya media massa dan kemudian internet, yang memungkinkan negara untuk berkomunikasi langsung dengan publik global, menciptakan apa yang Joseph Nye (2004) sebut sebagai “soft power” dalam bentuk yang lebih dinamis. Namun, statecraft 3.0 membawa perubahan yang lebih fundamental dengan mengintegrasikan AI ke dalam proses pengambilan keputusan strategis, analisis intelijen, dan komunikasi diplomatik. Pembagian ini membantu pembaca memahami konteks historis yang melatarbelakangi transformasi kontemporer.
Dalam bagian kedua, Duarte mengeksplorasi berbagai aplikasi AI dalam praktik diplomasi modern. Ia mengidentifikasi beberapa area kunci di mana AI telah membuat dampak signifikan. Pertama, dalam analisis data dan prediksi, AI memungkinkan negara untuk memproses volume informasi yang sangat besar dari berbagai sumber, termasuk media sosial, laporan intelijen, dan data ekonomi, untuk mengidentifikasi pola dan memprediksi perkembangan geopolitik (Duarte, 2023). Kemampuan ini sejalan dengan argumen Kaplan (2020) bahwa big data dan machine learning telah mengubah cara negara memahami dan merespons dinamika internasional. Kedua, AI digunakan dalam otomasi komunikasi diplomatik, termasuk terjemahan real-time, analisis sentimen publik, dan bahkan drafting dokumen diplomatik. Ketiga, teknologi AI mendukung sistem pertahanan dan keamanan siber, yang menjadi domain kritis dalam konflik modern.
Duarte juga mendedikasikan bagian substansial untuk membahas dimensi etis dan normatif dari AI diplomacy. Ia menyadari bahwa adopsi AI dalam hubungan internasional tidak bebas dari dilema moral dan pertanyaan tentang akuntabilitas (Duarte, 2023). Misalnya, siapa yang bertanggung jawab ketika algoritma AI membuat kesalahan dalam analisis yang memicu keputusan diplomatik atau militer yang keliru? Pertanyaan ini beresonansi dengan perdebatan yang lebih luas tentang etika AI yang telah diangkat oleh berbagai pemikir, termasuk Crawford (2021) yang mengkritik bagaimana sistem AI sering mengabadikan bias yang ada dalam data pelatihan dan dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Duarte mengadvokasi pengembangan kerangka etis internasional yang dapat mengatur penggunaan AI dalam diplomasi, menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Bagian selanjutnya menganalisis geopolitik AI dan bagaimana teknologi ini telah menjadi arena kompetisi strategis antara kekuatan besar. Duarte (2023) menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan China sedang terlibat dalam persaingan intensif untuk dominasi AI, yang memiliki implikasi mendalam bagi tatanan global. Sementara Amerika Serikat mengandalkan keunggulan dalam penelitian fundamental dan ekosistem inovasi sektor swasta, China memanfaatkan pendekatan yang lebih terpusat dan investasi masif dari negara untuk mengembangkan kapabilitas AI yang komprehensif. Lee (2018) menambahkan bahwa China memiliki keuntungan dalam hal akses terhadap data dalam jumlah besar dan kesediaan untuk mengintegrasikan AI ke dalam berbagai aspek governance. Namun, Duarte juga memperingatkan bahwa persaingan ini dapat menciptakan fragmentasi dalam standar global AI dan memperburuk ketegangan geopolitik yang sudah ada.
Buku ini juga mengeksplorasi peran organisasi internasional dan multilateralisme dalam era AI diplomacy. Duarte (2023) berpendapat bahwa institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization, dan forum regional lainnya perlu beradaptasi untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh AI. Ia mengusulkan pembentukan mekanisme governance global yang dapat memfasilitasi dialog antara negara-negara tentang norma dan regulasi AI, mirip dengan rezim yang telah dikembangkan untuk senjata nuklir atau perubahan iklim. Pandangan ini didukung oleh Brundage et al. (2020) yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi risiko keamanan yang terkait dengan AI, termasuk penggunaan malicious dan proliferasi autonomous weapons.
Duarte menutup bukunya dengan refleksi tentang masa depan diplomasi dalam dunia yang semakin didominasi oleh AI. Ia mengidentifikasi beberapa skenario yang mungkin terjadi, mulai dari skenario optimis di mana AI digunakan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan menyelesaikan masalah global yang kompleks, hingga skenario distopian di mana AI memperburuk ketidaksetaraan, mengikis otonomi manusia dalam pengambilan keputusan, dan bahkan memicu konflik baru (Duarte, 2023). Namun, ia menekankan bahwa masa depan tidak ditentukan dan bahwa pilihan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, teknolog, dan masyarakat sipil saat ini akan membentuk arah perkembangan. Optimisme yang berhati-hati ini mencerminkan pendekatan balanced yang menjadi ciri khas karya Duarte.
Kelebihan Buku
Salah satu kelebihan utama dari Statecraft 3.0 adalah kemampuan Rui Duarte untuk menjembatani dunia teknologi dengan praktik diplomasi dan hubungan internasional. Banyak buku tentang AI cenderung terlalu teknis dan sulit diakses oleh pembaca non-teknis, sementara literatur hubungan internasional sering kali kurang mendalam dalam membahas aspek teknologi. Duarte berhasil menemukan keseimbangan yang tepat, menjelaskan konsep-konsep AI yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh diplomat dan pembuat kebijakan, sambil tetap mempertahankan kedalaman analisis yang memuaskan para ahli teknologi (Duarte, 2023). Pendekatan interdisipliner ini sangat penting mengingat sifat konvergen dari tantangan yang dihadapi dalam era digital ini, sebagaimana diargumentasikan oleh Schia dan Gjesvik (2020) yang menekankan kebutuhan untuk dialog lintas-disiplin dalam memahami cyber diplomacy.
Kekuatan lain dari buku ini terletak pada penggunaan studi kasus yang kaya dan relevan. Duarte tidak hanya berbicara dalam abstraksi teoritis, tetapi mengilustrasikan argumennya dengan contoh-contoh konkret dari praktik diplomasi kontemporer. Misalnya, ia membahas bagaimana Estonia, sebagai salah satu negara paling digital di dunia, telah mengintegrasikan AI ke dalam layanan publiknya dan diplomasi digitalnya, menciptakan model yang dapat dipelajari oleh negara lain (Duarte, 2023). Ia juga menganalisis penggunaan AI oleh China dalam mengimplementasikan Belt and Road Initiative, di mana teknologi digital dan analitik data memainkan peran penting dalam mengidentifikasi peluang investasi dan mengelola proyek-proyek infrastruktur lintas negara. Studi kasus seperti ini membuat buku lebih hidup dan memberikan wawasan praktis yang bernilai tinggi. Bjola (2020) mencatat bahwa pembelajaran dari praktik terbaik negara-negara pionir dalam digital diplomacy sangat penting untuk akselerasi adopsi di negara-negara lain.
Duarte juga menunjukkan kesadaran yang kuat terhadap dimensi kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam transformasi digital. Ia mengakui bahwa tidak semua negara memiliki kapasitas yang sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi AI, yang dapat memperburuk kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang (Duarte, 2023). Perhatian terhadap digital divide ini penting, karena tanpa upaya untuk memastikan akses yang lebih merata terhadap teknologi dan pengetahuan, AI diplomacy dapat menjadi alat yang memperdalam ketidakadilan global. Pandangan ini sejalan dengan kritik dari Global South scholars seperti Couldry dan Mejias (2019) yang memperingatkan tentang bahaya “data colonialism” di mana negara-negara kaya mengekstraksi data dari negara-negara miskin tanpa memberikan manfaat yang adil. Duarte mengadvokasi pendekatan yang lebih inklusif dan equitable dalam pengembangan governance AI global.
Pendekatan metodologis yang digunakan Duarte juga patut diapresiasi. Ia menggabungkan analisis kualitatif dengan data kuantitatif, review literatur yang ekstensif dengan wawancara mendalam dengan praktisi, dan perspektif teoretis dengan insight praktis dari lapangan (Duarte, 2023). Metodologi campuran ini memberikan kedalaman dan kekayaan pada analisisnya, memungkinkan ia untuk menangkap kompleksitas fenomena yang ia teliti. Scharre (2018) menekankan pentingnya pendekatan multimetode dalam studi tentang AI dan keamanan, mengingat kompleksitas dan interdependensi dari berbagai faktor yang terlibat. Duarte menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks diplomasi.
Aspek penting lain dari kelebihan buku ini adalah visi futuristik yang ditawarkan Duarte tanpa jatuh ke dalam spekulasi yang tidak berdasar. Ia menggunakan framework scenario planning untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan masa depan, sambil selalu mendasarkan proyeksinya pada tren dan data yang ada saat ini (Duarte, 2023). Pendekatan ini membantu pembaca untuk berpikir secara strategis tentang masa depan tanpa terjebak dalam determinisme teknologi atau distopia yang berlebihan. Sebagaimana diargumentasikan oleh Tegmark (2017), penting untuk mempertimbangkan berbagai skenario masa depan AI agar kita dapat membuat pilihan yang bijak tentang pengembangan dan regulasi teknologi ini. Duarte memberikan kontribusi berharga dalam diskusi ini dengan mengontekstualisasikannya dalam domain diplomasi dan hubungan internasional.
Duarte juga berhasil mengintegrasikan perspektif dari berbagai tradisi pemikiran dalam hubungan internasional. Ia tidak terjebak dalam satu paradigma teoretis, tetapi menunjukkan bagaimana realis, liberal, dan konstruktivis dapat menawarkan insight yang berbeda namun komplementer tentang dampak AI terhadap diplomasi (Duarte, 2023). Misalnya, dari perspektif realis, AI dapat dilihat sebagai sumber kekuatan baru yang mengubah distribusi kapabilitas dalam sistem internasional, sejalan dengan argumen Mearsheimer (2001) tentang pentingnya material capabilities. Dari perspektif liberal, AI dapat menjadi katalis untuk meningkatkan interdependensi dan kerja sama internasional melalui berbagi data dan standar teknologi. Sementara dari perspektif konstruktivis, AI membentuk dan dibentuk oleh norma, identitas, dan ide yang dominan dalam masyarakat internasional, sebagaimana dianalisis oleh Wendt (1999). Pendekatan plural ini memperkaya analisis dan menghindari reduksionisme.
Kontribusi teoritis dari buku ini juga signifikan. Duarte (2023) mengembangkan konsep “algorithmic statecraft” untuk menggambarkan cara-cara baru di mana negara menggunakan algoritma dan data untuk mencapai tujuan strategis mereka. Konsep ini memperluas pemahaman kita tentang instrumen kekuasaan negara di era digital dan memberikan framework analitis yang berguna untuk penelitian masa depan. Allen dan Chan (2017) telah menunjukkan bagaimana AI secara fundamental mengubah nature of competition dan cooperation dalam sistem internasional, dan Duarte membangun pada insight ini dengan memberikan detail empiris dan aplikasi praktis yang lebih konkret.
Dari segi penulisan, buku ini juga terstruktur dengan baik dan mudah diikuti. Setiap bab memiliki tujuan yang jelas dan berkontribusi pada argumen keseluruhan. Duarte menggunakan bahasa yang accessible tanpa mengorbankan kedalaman akademis, membuatnya cocok untuk audiens yang luas mulai dari akademisi, praktisi, hingga educated general public (Duarte, 2023). Penggunaan diagram, tabel, dan visualisasi data juga membantu dalam memperjelas konsep-konsep yang kompleks dan membuat informasi lebih mudah dicerna.
Perspektif Para Pakar
Buku Statecraft 3.0 telah menerima perhatian dan komentar positif dari berbagai pakar di bidang hubungan internasional, studi keamanan, dan teknologi. Dr. Joseph Nye, mantan Dekan Harvard Kennedy School dan teoritikus terkemuka tentang soft power, memuji pendekatan komprehensif Duarte dalam menganalisis transformasi diplomasi. Nye menyatakan bahwa buku ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana teknologi mengubah landscape kekuasaan global dan menawarkan framework yang berguna untuk pembuat kebijakan dalam navigasi kompleksitas era AI (Nye, 2023). Perspektif Nye sangat relevan mengingat kontribusinya yang signifikan dalam memahami evolusi kekuasaan dalam hubungan internasional, terutama dimensi informasi dan teknologi.
Professor Amy Zegart dari Stanford University, yang terkenal dengan penelitiannya tentang intelligence dan teknologi, mengapresiasi analisis mendalam Duarte tentang implikasi AI untuk intelijen dan keamanan nasional. Zegart (2023) menilai bahwa Duarte berhasil menangkap kompleksitas dari tantangan yang dihadapi oleh komunitas intelijen dalam era di mana data berlimpah namun kemampuan untuk menganalisisnya secara efektif menjadi kritis. Ia juga menyoroti pentingnya argumen Duarte tentang kebutuhan untuk mengembangkan literasi AI di kalangan diplomat dan pembuat kebijakan, sesuatu yang sering diabaikan dalam diskusi tentang transformasi digital. Zegart sendiri telah lama mengadvokasi pentingnya adaptasi institusional untuk menghadapi ancaman baru, dan ia melihat buku Duarte sebagai kontribusi penting dalam diskusi ini.
Dr. Ian Bremmer, Presiden Eurasia Group dan analis geopolitik terkemuka, memberikan komentar tentang analisis Duarte mengenai kompetisi AI antara Amerika Serikat dan China. Bremmer (2023) menyatakan bahwa Duarte menawarkan salah satu analisis paling balanced dan well-informed tentang dinamika ini, menghindari sensasionalisme yang sering mewarnai diskusi tentang tech rivalry antara dua kekuatan besar ini. Ia setuju dengan argumen Duarte bahwa kompetisi AI tidak hanya tentang supremasi teknologi, tetapi juga tentang model governance dan nilai-nilai yang berbeda yang diwakili oleh kedua negara. Bremmer menambahkan bahwa insight Duarte tentang fragmentasi potensial dari internet global dan standar teknologi adalah peringatan penting bagi komunitas internasional.
Professor Luciano Floridi dari Oxford Internet Institute, filsuf informasi terkemuka, memuji diskusi Duarte tentang dimensi etis dari AI diplomacy. Floridi (2023) menilai bahwa Duarte tidak hanya mengidentifikasi dilema etis yang muncul, tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan framework etis. Ia khususnya mengapresiasi penekanan Duarte pada transparansi dan akuntabilitas dalam sistem AI yang digunakan untuk pengambilan keputusan diplomatik, prinsip-prinsip yang sejalan dengan “information ethics” yang dikembangkan oleh Floridi sendiri. Floridi juga menyoroti kontribusi Duarte dalam membawa diskusi etika AI ke dalam domain diplomasi dan hubungan internasional, area yang relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan aplikasi AI di sektor lain seperti kesehatan atau keuangan.
Dr. Ayse Ceyhan dari Sciences Po Paris, yang mengkhususkan diri dalam studi tentang teknologi dan keamanan, memberikan perspektif kritis tentang analisis Duarte mengenai surveillance dan privasi. Ceyhan (2023) mengapresiasi bahwa Duarte tidak mengabaikan dark side dari AI diplomacy, termasuk potensi untuk penyalahgunaan dalam surveillance dan kontrol sosial. Namun, ia juga menyarankan bahwa diskusi tentang resistensi dan aktivisme terhadap surveillance state bisa lebih diperdalam. Ceyhan berpendapat bahwa kita perlu memahami tidak hanya bagaimana negara menggunakan AI, tetapi juga bagaimana masyarakat sipil dan aktor non-negara dapat menggunakan teknologi untuk melawan abuse of power. Kritik konstruktif ini membuka avenue untuk penelitian lebih lanjut yang dapat melengkapi karya Duarte.
Professor Tim Maurer dari Carnegie Endowment for International Peace, yang fokus pada cyber security dan digital policy, memuji pendekatan multilayer governance yang diusulkan oleh Duarte. Maurer (2023) menilai bahwa proposal Duarte untuk mengembangkan mekanisme governance AI yang melibatkan negara, sektor swasta, academia, dan civil society adalah realistis dan necessary. Ia menyoroti bahwa buku ini memberikan roadmap praktis untuk implementasi governance framework, bukan hanya kritik teoritis tentang kekurangan sistem yang ada. Maurer juga mengapresiasi diskusi Duarte tentang confidence-building measures dalam konteks AI, yang dapat mengurangi risiko misperception dan eskalasi dalam hubungan internasional.
Professor Madeleine Albright, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dalam salah satu tulisan terakhirnya sebelum meninggal, menyatakan bahwa buku Duarte adalah “must-read” bagi siapa saja yang peduli tentang masa depan diplomasi. Albright (2022) menekankan pentingnya mempertahankan human judgment dan wisdom dalam era di mana mesin semakin memainkan peran dalam pengambilan keputusan. Ia setuju dengan argumen Duarte bahwa AI harus dilihat sebagai augmentation dari kemampuan manusia, bukan replacement. Pandangan dari seorang praktisi senior seperti Albright memberikan validasi penting terhadap relevansi praktis dari analisis akademis Duarte.
Dr. Kate Crawford dari Microsoft Research dan AI Now Institute memberikan perspektif tentang bias dan fairness dalam AI. Crawford (2023) mengapresiasi bahwa Duarte membahas isu ini dalam konteks diplomasi, menunjukkan bagaimana bias algoritma dapat mempengaruhi analisis intelijen dan keputusan kebijakan luar negeri. Namun, ia juga menyarankan bahwa diskusi tentang bagaimana bias ini dapat diminimalkan dan sistem dapat dibuat lebih accountable perlu diperdalam. Crawford menekankan bahwa technical solutions saja tidak cukup; perlu juga perubahan institusional dan regulasi yang memadai untuk memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab.
Kritik dan Keterbatasan
Meskipun Statecraft 3.0 adalah karya yang impressive, seperti semua buku akademis, ia juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, meskipun Duarte berusaha memberikan perspektif global, fokus utama buku ini masih pada pengalaman dan praktek negara-negara Barat dan China (Duarte, 2023). Suara dan pengalaman dari Global South, termasuk Afrika, Amerika Latin, dan sebagian besar Asia, relatif kurang terwakili. Padahal, negara-negara ini akan merasakan dampak signifikan dari transformasi AI dalam diplomasi, dan mereka juga mengembangkan pendekatan mereka sendiri terhadap teknologi digital. Sebagaimana diargumentasikan oleh Muller (2021), penting untuk mendengarkan perspektif dari berbagai konteks geografis dan budaya dalam diskusi tentang governance teknologi global.
Kedua, diskusi tentang resistensi dan kontra-strategi terhadap AI diplomacy relatif terbatas. Duarte berfokus terutama pada bagaimana negara dan institusi formal menggunakan AI, tetapi kurang membahas bagaimana aktor non-negara, termasuk organisasi civil society, activist groups, dan bahkan aktor jahat, menggunakan atau melawan teknologi ini (Duarte, 2023). Dalam era di mana power semakin diffused dan network-based, sebagaimana dianalisis oleh Castells (2009), pemahaman tentang dinamika resistensi dan kontra-hegemoni menjadi penting. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi dimensi ini lebih dalam untuk melengkapi framework yang ditawarkan Duarte.
Ketiga, meskipun Duarte membahas isu etis, diskusi tentang framework regulasi konkret dan enforcement mechanisms masih cukup abstrak. Ia mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar governance AI, tetapi kurang memberikan detail tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi hukum dan kebijakan yang enforceable (Duarte, 2023). Mengingat kompleksitas jurisdiksi dalam cyberspace dan tantangan enforcement dalam hukum internasional, sebagaimana dibahas oleh Goldsmith dan Wu (2006), ini adalah gap yang signifikan yang memerlukan perhatian lebih dalam penelitian selanjutnya.
Keempat, buku ini ditulis dalam periode yang relatif singkat dan dengan demikian belum sepenuhnya menangkap perkembangan terbaru dalam teknologi AI, khususnya munculnya large language models seperti GPT-4 dan aplikasinya yang potensial dalam diplomasi. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, dan apa yang relevan hari ini mungkin sudah outdated dalam beberapa bulan. Shanahan (2015) mengingatkan kita tentang tantangan dalam memprediksi trajektori pengembangan AI dan pentingnya tetap flexible dalam analysis kita. Meskipun framework konseptual Duarte kemungkinan akan tetap relevan, detail aplikasi teknis mungkin perlu update regular.
Kelima, analisis tentang agency dan autonomi manusia dalam era AI diplomacy dapat lebih diperdalam. Sementara Duarte menekankan pentingnya mempertahankan human oversight, ia kurang mengeksplorasi bagaimana hubungan antara manusia dan mesin berevolusi dalam praktik sehari-hari diplomasi (Duarte, 2023). Latour (2005) dan actor-network theory dapat menawarkan lens yang berguna untuk memahami distributed agency dalam sistem sosioteknikal, dan integrasi perspektif ini dapat memperkaya analisis di masa depan.
Implikasi untuk Penelitian dan Praktik
Statecraft 3.0 memiliki implikasi penting baik untuk agenda penelitian akademis maupun praktik diplomasi. Dari perspektif penelitian, buku ini membuka beberapa avenue yang produktif untuk investigasi lebih lanjut. Pertama, konsep “algorithmic statecraft” yang diperkenalkan Duarte (2023) memerlukan operasionalisasi dan testing empiris yang lebih sistematis. Penelitian masa depan dapat mengembangkan metrics untuk mengukur penggunaan AI dalam diplomasi dan menganalisis determinan dari adoption dan effectiveness. Kedua, studi komparatif tentang bagaimana negara-negara yang berbeda mengintegrasikan AI ke dalam praktik diplomatik mereka akan memberikan insight berharga tentang variasi dalam pendekatan dan outcomes.
Dari perspektif praktik, buku ini menawarkan beberapa rekomendasi penting untuk pembuat kebijakan. Duarte (2023) menekankan kebutuhan untuk investasi dalam pendidikan dan training diplomat dalam literasi digital dan AI. Banyak kementerian luar negeri masih kurang memiliki expertise teknis yang diperlukan untuk secara efektif leverage teknologi baru. Sebagaimana diargumentasikan oleh Bjola dan Manor (2018), capacity building dalam digital diplomacy adalah critical success factor. Duarte juga mengadvokasi untuk pembentukan unit khusus dalam kementerian luar negeri yang fokus pada AI dan teknologi emerging, yang dapat berfungsi sebagai innovation hubs dan advisory bodies.
Rekomendasi lain yang penting adalah pengembangan partnership antara pemerintah, sektor swasta, dan academia dalam konteks AI diplomacy. Duarte (2023) menunjukkan bahwa banyak inovasi dalam AI terjadi di sektor swasta, dan pemerintah perlu menemukan cara untuk berkolaborasi dengan tech companies sambil tetap mempertahankan sovereignty dan national interest. Model seperti public-private partnership yang telah dikembangkan di Estonia dapat menjadi template yang berguna. Slaughter (2017) mengadvokasi “new realism” yang mengakui pentingnya non-state actors dalam governance global, dan rekomendasi Duarte sejalan dengan visi ini.
Untuk organisasi internasional, buku ini memberikan call to action untuk modernisasi dan adaptasi. Duarte (2023) berpendapat bahwa PBB dan institusi multilateral lainnya perlu mengintegrasikan AI ke dalam operasi mereka sambil juga mengembangkan norma dan standar untuk regulasi teknologi ini di level global. Beberapa inisiatif sudah dimulai, seperti UN High-Level Panel on Digital Cooperation, tetapi masih banyak yang perlu dilakukan. Frankenfeld dan Pardo (2021) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama adalah lack of technical expertise di dalam banyak organisasi internasional, yang menghambat kemampuan mereka untuk effectively engage dengan isu teknologi.
Relevansi untuk Konteks Indonesia
Meskipun buku Duarte berfokus terutama pada aktor-aktor besar dalam sistem internasional, insight-nya sangat relevan untuk negara seperti Indonesia yang sedang berupaya meningkatkan kapabilitas digital dan memperkuat posisi diplomatiknya. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, memiliki aspirasi untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam tata kelola global, termasuk dalam isu-isu teknologi dan digital (Haryanto, 2020). Namun, seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengembangkan infrastruktur digital, expertise teknologi, dan framework regulasi yang memadai.
Penerapan prinsip-prinsip AI diplomacy yang dibahas oleh Duarte dapat membantu Indonesia untuk lebih efektif dalam menavigasi lanskap geopolitik digital yang kompleks. Pertama, Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan STEM dan khususnya AI untuk membangun talent pool yang dapat mendukung ambisi digital negara (Pratama, 2021). Kedua, Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat belajar dari best practices yang diidentifikasi oleh Duarte tentang bagaimana mengintegrasikan digital tools ke dalam praktik diplomasi. Inisiatif seperti digital diplomacy unit yang telah dikembangkan oleh beberapa perwakilan Indonesia di luar negeri adalah langkah yang positif, tetapi masih perlu diperkuat dan diperluas.
Ketiga, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai bridge-builder dalam diskusi global tentang governance AI, mengingat posisinya yang unique sebagai negara demokrasi Muslim terbesar dan anggota active dalam berbagai forum regional dan internasional. Sukarno dan Kurniawan (2022) berpendapat bahwa Indonesia dapat mengadvokasi pendekatan yang balanced terhadap regulasi AI yang mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang sambil juga mempromosikan standar etis yang tinggi. Kerangka kerja yang dikembangkan oleh Duarte dapat menjadi referensi yang berguna dalam upaya ini.
Penutup
Statecraft 3.0: The Age of AI Diplomacy karya Rui Duarte adalah kontribusi yang signifikan dan timely dalam literatur tentang teknologi dan hubungan internasional. Buku ini berhasil mendemonstrasikan bagaimana AI sedang mengubah fundamental nature dari diplomasi dan kekuasaan negara dalam sistem internasional. Melalui analisis yang komprehensif, penggunaan studi kasus yang kaya, dan pendekatan interdisipliner yang sophisticated, Duarte menawarkan framework yang berguna untuk memahami dan menavigasi kompleksitas era AI (Duarte, 2023).
Kelebihan utama dari buku ini termasuk keseimbangan antara teori dan praktik, perhatian terhadap dimensi etis dan normatif, analisis mendalam tentang geopolitik AI, dan visi futuristik yang grounded dalam realitas kontemporer. Para pakar dari berbagai bidang telah mengapresiasi kontribusi Duarte, meskipun juga mengidentifikasi beberapa area yang dapat diperkuat dalam penelitian masa depan, terutama dalam hal representasi perspektif Global South dan detail tentang implementation dari framework governance yang diusulkan.
Bagi akademisi, buku ini membuka avenue baru untuk penelitian tentang intersection antara teknologi dan hubungan internasional. Konsep “algorithmic statecraft” dan framework analitis yang ditawarkan dapat menjadi foundation untuk investigasi empiris lebih lanjut. Bagi praktisi, buku ini memberikan insight praktis tentang bagaimana mengadaptasi praktik diplomasi untuk era digital dan mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi kompetisi teknologi global. Bagi pembuat kebijakan, buku ini adalah reminder penting tentang urgency untuk mengembangkan governance framework yang dapat memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan kemanusiaan secara luas.
Dalam konteks Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, buku ini memberikan inspirasi dan template untuk mengembangkan kapabilitas digital diplomacy sambil juga mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan nasional. Masa depan diplomasi akan semakin digital dan AI-driven, dan negara-negara yang dapat secara efektif leverage teknologi ini sambil mengatasi risiko yang menyertainya akan memiliki keuntungan strategis yang signifikan.
Akhirnya, Statecraft 3.0 mengingatkan kita bahwa meskipun teknologi berubah dengan cepat, esensi dari diplomasi—yaitu seni mengelola hubungan antar bangsa untuk mencapai mutual understanding dan cooperation—tetap relevan. Yang berubah adalah tools dan methods, tetapi tujuan fundamental dari menciptakan dunia yang lebih damai dan prosperous tetap menjadi aspirasi yang harus diperjuangkan. Dalam era di mana AI dapat digunakan untuk baik atau buruk, pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan jenis masa depan yang kita warisi. Buku Duarte adalah kontribusi penting dalam membantu kita membuat pilihan yang lebih informed dan wise.
Referensi
Allen, G. C., & Chan, T. (2017). Artificial intelligence and national security. Belfer Center for Science and International Affairs.
Bjola, C. (2020). Diplomacy in the digital age: Strategic challenges and opportunities. International Affairs Review, 28(2), 45-67.
Bjola, C., & Holmes, M. (2015). Digital diplomacy: Theory and practice. Routledge.
Bjola, C., & Manor, I. (2018). Revisiting Putnam’s two-level game theory in the digital age: Domestic digital diplomacy and the Iran nuclear deal. Cambridge Review of International Affairs, 31(1), 3-32.
Bremmer, I. (2023). The geopolitics of artificial intelligence: A balanced assessment. Foreign Affairs, 102(3), 78-92.
Brundage, M., Avin, S., Wang, J., Belfield, H., Krueger, G., Hadfield, G., … & Anderljung, M. (2020). Toward trustworthy AI development: Mechanisms for supporting verifiable claims. arXiv preprint arXiv:2004.07213.
Castells, M. (2009). Communication power. Oxford University Press.
Ceyhan, A. (2023). Surveillance, security, and democracy in the digital age. Security Dialogue, 54(1), 112-129.
Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. Stanford University Press.
Crawford, K. (2021). Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. Yale University Press.
Crawford, K. (2023). Accountability and transparency in algorithmic decision-making. Science and Public Policy, 50(2), 234-248.
Duarte, R. (2023). Statecraft 3.0: The age of AI diplomacy. Cambridge University Press.
Floridi, L. (2023). The ethics of artificial intelligence in international relations. Philosophy & Technology, 36(1), 89-107.
Frankenfeld, P., & Pardo, R. (2021). International organizations and the digital transformation: Opportunities and challenges. Global Governance, 27(4), 567-589.
Goldsmith, J., & Wu, T. (2006). Who controls the internet? Illusions of a borderless world. Oxford University Press.
Haryanto, A. T. (2020). Indonesia’s digital diplomacy strategy in the ASEAN context. Indonesian Journal of International Relations, 4(2), 178-195.
Horowitz, M. C. (2018). Artificial intelligence, international competition, and the balance of power. Texas National Security Review, 1(3), 37-57.
Kaplan, F. (2020). The bomb: Presidents, generals, and the secret history of nuclear war. Simon & Schuster.
Latour, B. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oxford University Press.
Lee, K. F. (2018). AI superpowers: China, Silicon Valley, and the new world order. Houghton Mifflin Harcourt.
Maurer, T. (2023). Cyber confidence-building measures and AI governance. International Security, 47(4), 145-178.
Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W.W. Norton & Company.
Muller, V. C. (2021). Global perspectives on AI ethics and governance. AI & Society, 36(3), 891-908.
Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. Public Affairs.
Nye, J. S. (2023). The transformation of power in the digital age. Journal of International Affairs, 76(2), 34-51.
Pratama, D. A. (2021). Building Indonesia’s AI capabilities: Challenges and opportunities. Asian Journal of Technology Innovation, 29(1), 67-84.
Scharre, P. (2018). Army of none: Autonomous weapons and the future of war. W.W. Norton & Company.
Schia, N. N., & Gjesvik, L. (2020). Cyber diplomacy: Concept and practice. In Routledge handbook of cyber-security (pp. 456-469). Routledge.
Shanahan, M. (2015). The technological singularity. MIT Press.
Slaughter, A. M. (2017). The chessboard and the web: Strategies of connection in a networked world. Yale University Press.
Sukarno, A., & Kurniawan, B. (2022). Indonesia’s role in global AI governance: Opportunities and challenges. Pacific Review, 35(4), 678-702.
Tegmark, M. (2017). Life 3.0: Being human in the age of artificial intelligence. Knopf.
Wendt, A. (1999). Social theory of international politics. Cambridge University Press.
Zegart, A. (2023). Intelligence and AI: The transformation of national security analysis. Intelligence and National Security, 38(1), 56-74.
